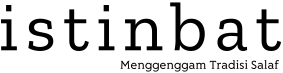SIKAP IMAM MUSLIM TERHADAP HADIS MU’AN’AN
Dalam literatur keislaman, terdapat pembahasan mengenai hadis mu’an’an. Secara terminologis, hadis mu’an’an adalah hadis yang sanadnya menggunakan redaksi ‘an (dari). Dalam studi kritik hadis, penggunaan redaksi ini sering dipertanyakan keabsahannya karena dinilai ambigu, tidak jelas, serta memungkinkan terjadinya ketidaksambungan riwayat, yakni perawi tidak secara langsung menerima hadis dari gurunya.[1]
BACA JUGA: Peran Hadis sebagai Sumber Tasyri’ dalam Islam
Al-Imam Muslim termasuk rawi yang menerima riwayat dengan redaksi ‘an, namun dengan syarat tertentu, yaitu adanya kemungkinan pertemuan (liqa’) antara perawi dan gurunya, serta adanya indikasi bahwa perawi tersebut tidak melakukan tadlis (penyamaran guru dalam periwayatan).[2]
Namun demikian, sikap al-Imam Muslim terhadap hadis mu’an’an ini oleh sebagian kalangan dianggap kurang ketat atau kurang cermat dalam proses verifikasi sanad. Menurut kelompok ini, keabsahan sebuah hadis baru dapat diterima apabila perawi secara pasti pernah belajar langsung dari gurunya. Kepastian tersebut, menurut mereka, tidak cukup hanya berdasarkan kemungkinan bertemu, tetapi harus disertai dengan indikator kuat, seperti adanya catatan atau riwayat bahwa keduanya pernah bertemu langsung dalam konteks belajar-mengajar. Hanya mengandalkan kemungkinan pertemuan dianggap lemah dan tidak cukup untuk memastikan adanya transmisi langsung dalam proses periwayatan hadis.[3]
Al-Imam Muslim berpendapat bahwa kemungkinan pertemuan (imkānul-Liqā’) antara perawi dan gurunya sudah cukup sebagai dasar untuk menerima keabsahan riwayat mu’an’an. Pandangan ini beliau dasarkan pada kesepakatan para ulama hadis lintas generasi, baik klasik maupun kontemporer, yang menganggap bahwa selama perawi tersebut tsiqah (terpercaya) dan hidup sezaman dengan gurunya, maka riwayatnya dapat diterima, meskipun tidak ada keterangan eksplisit mengenai pertemuan langsung.
Al-Imam Muslim bahkan mencela sikap berlebihan dari sebagian pihak yang mensyaratkan adanya ketetapan pasti telah bertemu (itsbātul-liqā’) dalam setiap riwayat mu’an’an. Menurut beliau, pandangan semacam ini merupakan penyimpangan dari manhaj para ulama hadis, serta tergolong sebagai pemikiran baru yang diada-adakan dalam agama (bid‘ah) karena tidak memiliki landasan dari generasi ulama sebelumnya.[4]
Asy-Syarif Hatim bin ‘Arif al-‘Auni, menilai bahwa jika syarat “pasti bertemu” diterapkan secara ketat, maka akan banyak hadis sahih yang terabaikan, bukan karena kelemahan sanad atau isi matannya, melainkan karena minimnya data biografis yang tersedia untuk memastikan hubungan langsung antarperawi. Dalam sejarah, biografi para ulama jarang sekali mencatat siapa saja yang pernah mereka temui secara langsung. Informasi yang umumnya dituliskan terbatas pada tanggal lahir, wafat, dan perjalanan ilmiah, bukan daftar semua individu yang pernah berinteraksi dengan mereka.[5]
Lebih jauh, jika syarat eksplisit “pernah bertemu” diterapkan, maka hal tersebut akan menuntut upaya yang tidak realistis, yakni harus mengikuti setiap aktivitas perawi secara langsung agar riwayatnya benar-benar bisa dipastikan. Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan induktif melalui indikator waktu dan tempat seperti diketahui bahwa seorang perawi pernah mengunjungi kota tertentu di mana gurunya tinggal merupakan salah satu cara valid dalam memastikan kemungkinan pertemuan menurut mayoritas ulama hadis.[6]
Penerimaan al-Imam Muslim terhadap hadis mu’an’an tidak dapat dianggap sebagai bentuk ketidakcermatan atau sikap longgar dalam kritik sanad. Justru sebaliknya, pandangan beliau menunjukkan kedalaman metodologi dalam memahami tradisi periwayatan hadis. Menurut beliau, hadis mu’an’an tetap dapat dijadikan hujjah, selama tidak terdapat indikator yang menunjukkan bahwa perawi tersebut tidak pernah bertemu dengan gurunya.
Dengan demikian, validitas hadis mu’an’an bergantung pada ketiadaan bukti yang menunjukkan adanya keterputusan. Oleh karena itu, pendekatan al-Imam Muslim tidak mengabaikan aspek kehati-hatian, melainkan menuntut adanya kajian yang menyeluruh dan kompeten terhadap semua data biografis dan historis yang tersedia. Hanya dengan penelitian yang utuh dan mendalam inilah kemungkinan celah yang menyebabkan penolakan terhadap hadis dapat dihindari. Maka, pendekatan ini bukanlah bentuk kelonggaran, melainkan bentuk standar ilmiah yang proporsional dan realistis dalam menghadapi keterbatasan data sejarah.
Sikap sebagian pembesar ulama hadis seperti Imam al-Bukhari, ‘Ali ibn al-Madīni, dan lainnya yang tampak lebih ketat daripada al-Imam Muslim dalam menilai hadis mu’an’an, tidak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Penerapan mereka yang lebih selektif justru dilakukan atas dasar kehati-hatian (iḥtiyāṭ), penyaringan ketat, serta usaha untuk memperkuat kualitas riwayat yang mereka kumpulkan dalam karya-karya monumental mereka.
Dengan demikian, harus dibedakan secara tegas antara prinsip dan penerapan. Dalam hal prinsip, kita tidak boleh terlalu longgar karena akan merusak kekokohan bangunan ilmiah hadis, namun juga tidak boleh terlalu ketat hingga menyebabkan terhambatnya proses kodifikasi dan transmisi ilmu. Prinsip ilmiah yang ideal adalah prinsip yang proporsional, konsisten, dan dapat diterapkan secara universal terhadap semua objek studi, tanpa diskriminasi atau kekakuan metodologis.
Adapun dalam tataran penerapan, seorang muhaddits memiliki ruang ijtihad untuk menentukan kriteria teknis yang sesuai dengan tujuan dan karakter karya yang sedang ia susun. Oleh karena itu, pendekatan ketat dalam praktik penulisan hadis tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap prinsip-prinsip umum yang lebih inklusif dalam kritik sanad.[7]
BACA JUGA: Hadis Nabi; Antara Syiah dan Ahlusunah
RIAN MAULIDI/ISTINBAT
Muhammad Mahmud Ahmad Bakkar, Bulughul-Amal min Mushthalahil-Hadis war-Rijal, I/240, Darus Salam.
Nuruddin Itr, Manhajun-Naqd fi Ulumil-Hadits, I/352, Darul Fikr.
Muhammad Abdul Hayyi al-Lakhnawi al-Hindi, Zhufrul-Amani bi Syarhi Mukhtasharus-Sayyid as-Syarif al-Jurjani fi Mushthalahul-Hadits, I/219, Darus Salam.
[2]Al-Imam Muslim Bin Al Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim, I/22, Darul Kutub Al Ilmiyah.
[3]Asy-Syarif Hatim bin ‘Arif al-‘Auni, Al-Intifa’ bi Munaqosyatil-Kitab Al-Ittishal wal-Inqitha’, hlm. 41, ( PDF: https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_0513_201808)
[4]Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, Shahih Muslim, I/22, Darul Kutub Al Ilmiyah.
[5]Asy-Syarif Hatim Bin ‘Arif Al-‘Auni, Al-Intifa’ Bi Munaqasyatil-Kitab al-Ittishal wal-Inqitha’, hlm. 36, ( PDF: https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_0513_201808)
[6]Ali Sulaiman Abi ‘Ubaidah Masyhur bin Hasan, Bahjatul-Muntafi’ Sharhu Juz`i Ulumil-Hadits fi Bayanil-Muttashil wal-Mursal wal-Mauquf wal-Munqhathi’ (Urdun: Darul Itriyah, cet. 1, 1428 H)
[7] Asy-Syarif Hatim bin ‘Arif al-‘Auni, Al-Intifa’ Bi Munaqasyatil-Kitab Al-Ittishal wal-Inqitha’, hlm. 46 ( PDF: https://archive.org/details/alfirdwsiy2018_gmail_0513_201808)
Asy-Syarif Hatim Bin ‘Arif al-‘Auni, Ijma’ul-Muhadditsin ala Adami Isytirathil-Ilmi bis-Sima’i fil-Hadis al-Mu’an’ani bainal-Muata’ashirina, hlm. 15,19, 29, 31, 34, 37, Dar Alimil Fawaid.