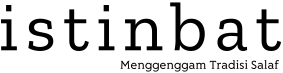Tafsir Polemik Demokrasi: Antara Demokrasi dan Egoisme
Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, dan kaum professional.
Wacana tentang demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan, sehingga tema pembicaraan antara lain; “Islam dan Demokrasi”, “Politik dan Demokrasi”, “Hukum dan Demokrasi”, dan tema lainnya. Karena itu, demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, seperti yang telah diakui oleh Moh. Mahfud MD, bahwa ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokarsi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.[1]
Demokrasi telah menjadi topik polemik yang tak kunjung surut. Sejak diperkenalkan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, demokrasi tampak menjanjikan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Namun, dalam praktiknya demokrasi seringkali melahirkan berbagai persoalan, baik secara teoritis maupun praktis. Pertanyaan sederhana yang dikemukakan berkaitan dengan kata demokrasi adalah apakah hakikat demokrasi itu?
Pemahaman hakikat demokrasi secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, “demos-cratein” atau “demos-cratos” adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.[2]
Sementara hakikat demokrasi secara terminologis ialah seperti yang dinyatakan oleh Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[3]
Secara historis, demokrasi berakar dari peradaban Yunani Kuno, khususnya di kota Athena, dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM. Demokrasi yang dipraktikkan di masa itu, berbentuk demokrasi langsung (direct democracy) artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.[4]
Namun, sistem ini sempat tenggelam dalam era feodalisme, kehidupan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Karena itu, di era ini disebut dengan abad kegelapan, sebab alam demokrasi yang telah dibangun sejak Yunani Kuno telah mati.
Akan tetapi, menjelang akhir abad pertengahan, lahirlah Magna Charta (Piagam Besar) sebagai piagam perjanjian yang memuat dua prinsip yang sangat mendasar; adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Hal ini menyebabkan munculnya dua gerakan yaitu gerakan renaissance dan gerakan reformasi. Gerakan ini lahir di Barat, karena adanya kontak dengan dunia Islam saat berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan.[5]
Dalam konteks global saat ini, demokrasi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Banyak negara yang secara formal menganut demokrasi, tetapi secara subtansial masih jauh dari prinsip-prinsip dasarnya. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Salah satu polemik yang mencuat tajam adalah perdebatan antara demokrasi dan syariah dalam konteks Islam. Sebagian kalangan memandang demokrasi sebagai sistem yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan, karena menempatkan suara mayoritas di atas hukum Tuhan. Mereka berargumen seperti itu, berdasarkan ayat al-Quran; Q.S. Yusuf: 40
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِۗ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ٤٠
Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini menegaskan supremasi nilai dan hukum Tuhan, bukan menolak segala bentuk ijtihad manusia dalam pengelolaan kekuasaan.[6]
Dalam tafsir lain, menyatakan bahwa demokrasi bisa kompatibel dengan Islam, sejauh prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan (‘adl), dan kebebasan berpendapat (hurriyyah) dijunjung tinggi. Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan hal ini adalah QS. Asy-Syura: 38;
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۚ ٣٨
“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;
Ayat ini dijadikan dasar bagi ulama yang mendukung partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah (syura) dalam Islam merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang mendekati prinsip demokrasi.
Syekh Wahbah az-Zuhaili menafsiri ayat وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ di atas, dengan perintah agar bermusyawarah dalam segala urusan, sebab dengan bermusyawarah segala urusan seperti memutuskan tindak langkah, mencapai tujuan, itu dapat berjalan dengan baik dan stabil, karena yang dimaksud dengan musyawarah sendiri adalah saling bertukar pendapat untuk mencari jalan keluar yang benar dan tepat.[7]
Prinsip musyawarah ini merupakan salah satu prinsip hidup yang dapat menunjukkan jalan keluar segala persoalan, baik dalam hal keputusan hukum, melantik seorang pemimpin, mengatur sebuah organisasi, menstabilkan jalannya pemerintahan, sampai urusan rumah tangga seperti memasak makanan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, Imam Ibnu al-Arabi berkomentar mengenai musyawarah, “Musyawarah adalah ikatan bagi kelompok dan alat untuk menjelajahi pikiran”.[8]
BACA JUGA: Tafsir Qurani atas Konflik dan Ketegangan Antarbangsa
Tafsir ini memperluas pemahaman tentang tatanan hidup yang mengedepankan nilai prinsip musyawarah, dalam artian menganggap suara rakyat lebih tinggi dampak suara individu seorang pemimpin, yakni mengedepankan demokrasi. Tafsir ini memperluas pemahaman demokrasi bukan sebagai sistem nilai Barat yang kaku, akan tetapi sebagai mekanisme yang dapat diperkaya oleh nilai-nilai lokal dan religius. Dalam kerangka ini, demokrasi dipandang sebagai wasilah (sarana), bukan sebagai ghayah (tujuan akhir).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar. Indonesia menghadapi dilema tersendiri dalam membumikan demokrasi. Reformasi 1998 menjadi tunggak penting yang membuka ruang demokratisasi secara luas, mulai dari kebebasan pers, multipartai, hingga pilkada langsung. Namun, dibalik pencapaian itu muncul tantangan besar, seperti politik uang, korupsi, oligarki, hingga polarisasi identitas menjadi ancaman nyata bagi demokrasi substansif.[9]
Fenomena di atas menambah kesempitan tafsir demokrasi, bahkan dengan retorika populis seringkali pemimpin Indonesia menggiring opini publik hingga mempersempit ruang kritik. Padahal, demokrasi yang seharusnya itu membuka ruang dialog, malah justru terjebak dalam perang wacana dan kabar berita hoaks.
Disinilah letak pentingnya melihat demokrasi bukan sebagai produk akhir, melainkan sebagai proses yang terus-menerus dikaji dan diperbaiki dengan mengikuti dinamika sosial politik. Karena demokrasi yang mapan tidak lahir dalam semalam, bahkan tumbuh dari pendidikan politik, penguatan civil society, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Bashri, “Tidaklah saling bertukar pendapat sebuah masyarakat atau bangsa kecuali mereka mendapatkan petunjuk jalan keluar yang paling maslahat”.[10]
Polemik tentang demokrasi tidak akan berhenti dalam waktu dekat, sebab demokrasi sendiri bukan sistem absolut, melainkan tatanan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan dinamika kekuasaan. Oleh karena itu, tugas kita hanya mempertahankan demokrasi sebagai prosedur, tetapi menegakkannya sebagai nilai.
Demokrasi tanpa moralitas dan akuntabilitas hanya akan menjadi kendaraan bagi kepentingan segelintir elit. Demokrasi yang bisa ditoleransi atau bahkan dianjurkan itu demokrasi yang menjamin maslahat dan tidak melanggar syariat, seperti menjaga prinsip musyawarah, menegakkan keadilan, dan menghindari kediktatoran.[11]
Oleh karena itu, sebagaimana Hadits Riwayat at-Tirmidzi, “ketika sebuah negara pemimpinnya fungsional, para elit negara dermawan, dan segala urusan berasaskan musyawarah, maka hidup di permukaan bumi lebih baik daripada alam bawah tanah. Dan sebaliknya, ketika para pemimpin negara sedang disfungsi, para miliader pada egois, dan segala urusan berada dalam genggaman wanita, maka alam bawah tanah (mati) lebih baik daripada permukaan bumi (hidup).”[12]
Saiful Anwar/Istinbat
BACA JUGA: Menepis Tafsir Feminis
[1] Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, hal. 5-6, Yogyakarta; Gema Media, 1999
[2] Kleden Ignar, Melacak Akar Konsep Demokrasi, hal. 5, Yogyakarta, 2000
[3] Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, hal. 8, Yogyakarta; Gema Media, 1999
[4] Ubaidillah A, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, hal. 169, Cet. Pertama, Jakarta; IAIN Jakarta Press, 2000
[5] Ibid. Hal. 170-171
[6] Mushtafa asy-Syami, al-Mauqi’ al-I’lami, Maktab al-Manshur al-Hasyimi al-Kharasani
[7] Syekh Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, XXV/78, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Bairut-Lebanon; Cet. Pertama, 1991 M | 1411 H.
[8] Imam Ibnu al-Arabi, Ahkamul-Quran, IV/1656, Maktabah Syamilah
[9] Ubaidillah A, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, hal. 188, Cet. Pertama, Jakarta; IAIN Jakarta Press, 2000
[10] Syekh Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, XXV/81-82, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Bairut-Lebanon; Cet. Pertama, 1991 M | 1411 H.
[11] Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Syariatullah al-Khalidah, hal. 8, Hai’ah ash-Shafwah al-Malikiyah, Cet. Ketiga, 2021 M | 1441 H.
[12] Syekh Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, XXV/87, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Bairut-Lebanon; Cet. Pertama, 1991 M | 1411 H.