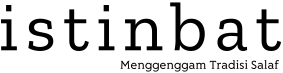Mengukur Maslahat
Pada edisi kali ini penulis tertarik membahas tentang mashlahah mursalah, salah satu dalil kontroversial yang banyak diminati oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terselubung di balik layar. Selain kontroversial, orang yang lihai akan mudah menjadikannya alat untuk mengelabui publik dengan mengenakan topeng agama dan menggunakan senjata ‘maslahat’ yang sebenarnya bukan untuk kepentingan bersama.
Untuk itu, hal pertama yang harus kita pahami adalah definisi maslahah itu sendiri, lalu dilanjut dengan memahami maslahah mursalah.
Maslahah pada dasarnya adalah ungkapan dalam menuai manfaat dan menolak kerusakan.[1] Sedangkan maslahah mursalah menurut Syekh al-Bhuti adalah “Segala bentuk manfaat yang berada di bawah naungan tujuan Syari’[2] (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tanpa ada dalil yang mendukung atau menolak”.[3] Dalam definisi ini sudah terkandung arti mursalah yang berarti tidak memiliki dukungan atau penolakan dari dalil syariat.
Lebih jelas lagi, Ulama Malikiah -yang dikenal paling getol menggunakan dalil ini- menyebutkan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi saat menggunakannya. Pertama, sejalan dengan tujuan Syari’ dan tidak mentiadakan dalil hukum yang sudah ada. Kedua, rasional serta mudah diterima akal. Ketiga, digunakan dalam hal yang bersifat mendesak atau untuk menghilangkan kesulitan umat. Keempat, nyata dan tidak semu. Kelima, universal, bukan hanya untuk perorangan, ras atau golongan tertentu.[4]
Contoh hukum yang bersumber dari maslahah mursalah adalah kemaslahatan bagi negara Islam dalam mewajibkan penduduknya untuk membayar pajak, khususnya saat kas negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tentara, pengokohan benteng dan penolakan pada musuh. Contoh lain adalah kemaslahatan mempelajari gramatika Arab, pembukuan ilmu Usul Fikih, pelajaran al-Jarh wa at-Ta’dil, Filsafat dan Anatomi. Kemaslahatan ini tidak memiliki dalil yang mendukung atau menolak. Namun didalamnya tersimpan satu tujuan syariat yang dalam hal ini adalah menjaga agama.[5]
Sepintas mudah. Namun dalam penerapannya pada sebuah permasalahan, ada yang terkesan terburu-buru, dan ada yang lambat berlari. Misalnya, statemen ulama tentang tidak adanya hukuman pengasingan pada perawan yang berzina setelah menjalani hukuman pertama, cambuk seratus kali, karena khawatir kejelekannya semakin menjadi-jadi.[6] Prof. Dr. Abdul Karim An-Namlah menjadikan kasus ini sebagai contoh dari maslahah mursalah. Sedangkan Prof. Ali Hasbullah dalam karangannya Ushulut Tasyri’ al-Islami menyatakan bahwa maslahah mursalah dalam kasus ini mampu menerjang dan mengalahkan isi hadis:
البِكرُ بِالبِكْر جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عَامٍ
“Perawan dan perjaka yang berzina dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun.”
Sebenarnya kasus ini merupakan pendapat ulama Hanafiah yang berlandaskan pada ayat:
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
“Maka cambuklah masing-masing dari keduanya seratus cambukan”
Imam Sarakhsi yang merupakan pakar ilmu Usul mazhab Hanafi berkesimpulan tentang ayat ini, bahwa cambukan dijadikan had atau hukuman. Andaikan masih harus ada pengasingan, maka itu melebihi isi nash dan merupakan bentuk dari naskh atau peralatan hukum, dan dalil yang bersifat mutawatir -seperti ayat Al-Quran diatas- tidak bisa di ralat oleh dalil yang ahad, (diriwayatkan beberapa orang saja). Bahkan hukuman pengasingan hanyalah takzir yang urusannya di pasrahkan kepada pemerintah[7]. Sampai disini kita tahu bahwa statemen di atas memiliki dalil, dan sudah barang tentu bukan termasuk contoh dari mashlahah mursalah.
Selain itu, ada yang berasumsi bahwa Imam Malik -pelopor dalil ini- mempersempit cakupan dalil yang bersifat umum dan membatasi dalil yang mutlak menggunakan maslahah mursalah. Contoh kasus yang laris digunakan dalam hal ini adalah pemukulan pada tersangka pelaku kriminal agar mengakui tindakan pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Hukum ini jelas menyalahi sabda Nabi:
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
“Saksi bagi pendakwa dan sumpah bagi terdakwa”.
Al-Bhuthi dalam hal ini telah melakukan penelitian, kemudian secara tegas menyatakan bahwa fatwa itu bukanlah milik Imam Malik. Bahkan merupakan pendapat pribadi Sahnun, penulis kitab al-Mudawwanah milik Imam Malik. Hanya saja, karena kitab itu merupakan riwayat Sahnun dari Abdurrahman, dari Imam Malik, ada saja kesamaran pendapat antara yang murni milik Imam Malik dan yang di munculkan Sahnun secara pribadi.[8] Oleh karenanya, setelah kerangka Maslahah Mursalah matang, orang yang hendak menggunakannya harus banyak tahu dalil, agar maslahah yang digaungkan memang muncul dari tidak adanya dalil bukan dikarenakan krisis pengetahuan.
Oleh: Syukron Makmun
Referensi dan catatan kaki:
[1] Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfa, Vol. I, hal. 174, Cet. Darul Kutub Al-Ilmiah
[2] Allah
[3] Syekh Sa’id Ramadhan al-Bhuthi, Dhawabithul Maslahah, hal. 330
[4] Dr. Abdul Karim Zidan, al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh, hal. 242, Cet. Muassasah ar-Risalah
[5] Syekh Sa’id Ramadhan Al-Bhuthi, Dhawabithul Maslahah, hal. 350
[6] Prof. Dr. Abdul Karim Namlah, al-Jami’ Li Masaili Ushulil Fiqh, hal. 390, Cet. Maktabah Ar-Rusyd
[7] Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl As-Sarakhsi, Vol. 9, Hal. 73, Cet. Darul Fikr, Bairut, Lebanon
[8] Syekh Sa’id Ramadhan Al-Bhuthi, Dhawabithul Maslahah, hal. 338