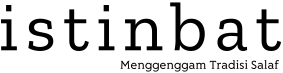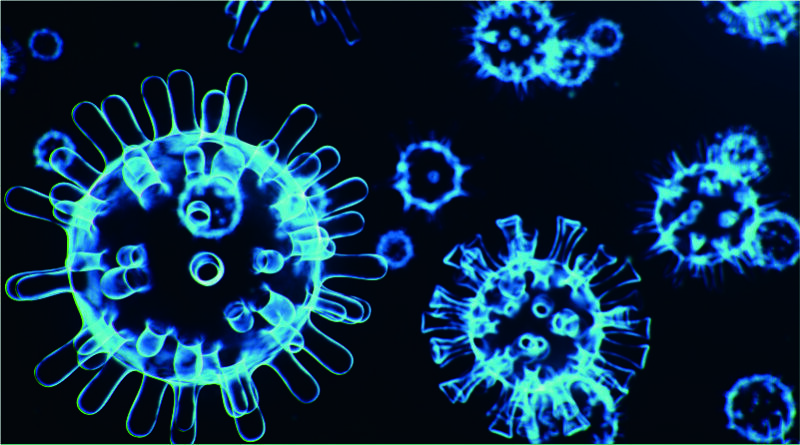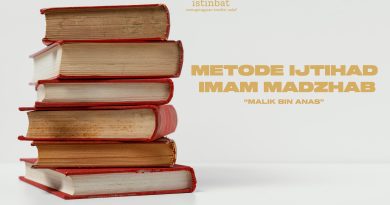Physical Distancing Dalam Bingkai Ushul Fiqh
Dewasa ini kita di kagetkan dengan munculnya virus yang sangat berbahaya. Covid-19, virus yang mulanya berasal dari negara tirai bambu ini, kini sudah menyebar sampai ke seluruh belahan dunia. Banyak negara yang sudah memberlakukan kebijakan Lock Down, semua aktifitas di batasi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang berkumpulnya orang banyak. Protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sudah lama di sosialisasikan sejak awal wabah ini menyebar. Hal ini guna memutus mata rantai virus yang dinilai cepat dan mudah menular dari satu orang ke orang lainnya. Tercatat sampai sekarang (8/10) sudah ada 1.049.810 orang yang meninggal akibat virus ini, dari total 36.002.827 orang yang terbukti pusitif terjangkit corona di seluruh dunia1.
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa virus ini memang benar-benar ada. Penyebaran virus ini bisa melalui droplet atau tetesan cairan saat seseorang bersin, batuk, berbicara, bahkan ketika bernafas. Oleh karenanya, para pakar menganjurkan untuk selalu melakukan Physical Distancing (red; menjaga jarak) di mana saja.
Adapun dalil yang menjadi prinsip terbentuknya peraturan Physical distancing adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang berbunyi:2
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ
Artinya: “Tidak ada penyakit yang menular, dan tidak ada prasangka jelek, dan tidak ada hâmah (ruh korban pembunuhan yang menjelma sebagai burung hantu untuk membalas dendamnya), dan tidak ada shafar (ular dalam perut manusia yang akan menyakitinya ketika lapar), dan larilah dari majdzum (penderita penyakit kusta) sebagai mana kamu berlari dari singa”.
Hadis mengenai Judzam juga disinggung dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur Ibnu Abi Aufa:
كَلِّمِ الْمَجْذُوْمَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ
Artinya: “Ajaklah majdzum (penderita penyakit kusta) berbicara, sedangkan di antara kamu dan dia berjarak satu atau dua tombak”
Sekilas, kedua hadis ini sudah cukup untuk dijadikan landasan dalam mewajibkan Physical Distancing. Hanya saja, jika keduanya dikaji dari sudut pandang ushul fiqh, maka akan kita temukan berbagai macam perspektip dari berbagai sudut pandang.
Pertama, Imam al-Qhadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Imam Ibnu Baththal berpendapat bahwa Lafadz لاعدوى merupakan lafazh ‘âm yang di-takhshish dengan lafadz فر من المجذوم dalam hadis sebelumnya. Lafadz لاعدوى merupakan lafazh ‘âm karena ditinjau dari sisi shîgat-nya yang dalam hal ini adalah an-nakiroh fî siyâqin-nafyi (lafadz nakiroh dalam susunan nafyi). Dengan begitu, lafazh tersebut memiliki afrâd atau bagian-bagian yang mencakup seluruh macam penyakit. Hanya saja, keumuman lafazh telah ini di takhshish (dipersempit hukumnya) oleh lanjutan hadisnya, sehingga memunculkan kesimpulan bahwa tidak ada penyakit yang menular di dunia ini yang harus dihindari kecuali kusta dan sejenisnya3.
Kedua, Syeikh Badruddin al-‘Ainî dalam kitabnya Umdat al-Qârî, menyatakan bahwa hadis di atas bersebrangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur sahabat Jabir4, bahwa Rasulullah pernah memegang tangan penderita kusta lalu meletakkannya di piring yang dibuat makan bersama dengan Beliau, kemudian Beliau berkata, “Makanlah! seraya menyebut nama Allah, percaya kepada-Nya dan berserah dirilah kepada-Nya 5.
Dalam menanggapi kontradiksi antar hadis, Ulama memiliki perspektif yang berbeda. Sayyidina Umar, Imam Isa bin Dinar, dan beberapa Ulama’ salaf menyatakan, bahwa hadis yang memerintahkan untuk menjauhi pengidap penyakit kusta di-nasakh dengan hadis riwayat Abu Dawud yang mengindikasikan bolehnya bergaul dengannya.
Sementara Ulama lain lebih cenderung untuk menggunakan thoriqot at tarjih (metode tarjih) yang dalam istilah ushul fiqh adalah:
بيان مزية أحد الدليلين على الآخر
Menjelaskan adanya kelebihan (nilai otentik) pada satu dari dua dalil6.
Maksud men-tarjîh di sini adalah, mengunggulkan hadis-hadis yang menyatakan tidak adanya penyakit yang menular, serta menstatuskan dlaif atau syadz hadis yang bertentangan dengannya.
Sebagian Ulama lain lebih mengunggulkan kebalikannya, yaitu redaksi yang menekankan kita untuk menjauh dari orang penderita kusta, karena hadis yang mengharuskan untuk menjauhinya lebih kuat secara sanad dan jalur periwayatannya lebih banyak. Hal semacam ini dalam ushul fiqh akrab disebut dengan metode ta’âdul wat-tarâjih bikatsratil-adillah yaitu mengunggulkan salah satu dari beberapa dalil yang bertentangan dengan menitik-tekankan kuatnya sanad dan banyaknya jalur periwayatan7.
Terlepas dari beberapa perspektip di muka, ada pandangan lain dari sisi ushul fiqh dalam menyikapi Tarik ulur antara kedua hadis di muka, yaitu dengan memprioritaskan thariqat al-jam’i wa at-taufiq, yakni mengkompromikan beberapa dalil yang bertentangan melalui beberapa sudut pandang yang memungkinkan8. Hal ini diberlakukan karena tarjih hanya bisa diimplementasikan ketika dalil-dalil yang bertentangan tidak mungkin lagi dikompromikan9. Metode ini adalah rangkaian dari metode Qaidah Ushuliyah “I’mâlud-dalilaini awlâ min ihmâli ahadihimâ” yang lumrah dipakai oleh Ulama ushul ketika di hadapkan dengan dalil-dalil yang saling berbenturan (ta’ârudl) secara dzahir10. Di antara Ulama yang mengusung metode ini dalam menyikapai hadis mengenai perintah menjauh dari penderita judzam di muka adalah Ibn Hajar al-Asqalani.
Ada beberapa maslak (metodologi) yang di kutip oleh Imam Ibnu Hajar untuk mengkompromikan hadis-hadis yang telah di sebutkan di atas11.
Pertama, mengarahkan perintah tersebut pada tujuan irsyad (anjuran) saja, sehingga shigat amar dalam dalam lafazh فر من المجذوم tidak lagi memunculkan hukum wajib sebagaimana pendapat imam Ibnu Khuzaimah yang diikuti oleh imam at-Thahawi. Sedangkan Imam al-Baji mengarahkan shigat amar di sini pada hukum ibâhah (boleh) berdekatan dengannya12. Sementara Syeikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengarahkannya pada tujuan syafaqah (kasih sayang), karena Nabi tidak mencegah umat-Nya kecuali untuk melakukan hal-hal yang mengandung dharar (bahaya)13.
Mengenai qarinah (indikator) yang memalingkannya dari hukum wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di muka, bahwa Nabi pernah makan satu piring dengan penderita judzam. Dengan demikian, shigat amar dalam lafazh فر من المجذوم tidak dimaknai sebagai hakikat lagi14.
Kedua, tidak ada satupun penyakit yang menular kecuali atas kehendak Allah SWT. Adapun perintah menjauhi penderita penyakit kusta bukan berarti mengindikasikan bahwa penyakit kusta itu menular, hanya saja ditujukan untuk menolak stigma menularnya penyakit kusta15. Hal ini dalam konteks ushul fiqh lumrah disebut dengan saddudz-dzarî’ah16.
Terlepas dari perselisihan Ulama dalam meyikapi hadis yang berkenaan dengan perintah untuk menjauhi orang yang terjangkit penyakit kusta, hal yang harus diperhatikan juga adalah, bahwa physical distancing dengan acuan hadis tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang disinyalir menimbulkan maslahat yang bersifat general, meski paradigma yang beredar di sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak menimbulkan maslahat. Oleh karena itu penting kiranya untuk mengkaji kebijkan tersebut dari sudut pandang maslahat dalam ranah syariat.
Imam al-Ghazali mendifinisikan maslahah dengan segala hal yang di maksudkan untuk menjaga maqashid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat), yang terklasifikasi pada menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan17. Adapun kebijakan pemerintah tersebut, dengan mempertimbangkan definisi maslahah yang telah dipaparkan oleh Imam al-Ghazali tadi merupakan kebijakan yang mengandung maslahat, karena selaras dengan salah satu maqhasid asy-syariah yang berupa menjaga diri (hifzhu an-nafs), sebab tujuan diberlakukannya kebijakan physical distancing adalah menjaga masyarakat dari penyakit yang dapat menular secara alami, sebagaimana perintah Nabi untuk menjaga jarak ketika berkomonikasi dengan orang yang terjangkit penyakit kusta. Di samping itu, maslahat yang di timbulkan bersifat general, dan tidak tertentu pada satu individual. Dengan begitu, perdebatan mengenai berbagai perspektip dalam menyikapi physical distancing menjadi selesai. Sebab, suatu khilaf akan menjadi final (tidak lagi berlaku) dengan adanya keputusan langsung dari pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama18. Hal ini berdasarkan sikap Rasulullah SAW ketika salah seorang utusan Bani Tsaqif menderita penyakit kusta yang dengan mengirim surat yang bertuliskan “انا قد بايعناك فارجع” (sungguh Kita telah membai’atmu maka pulanglah!).
Menurut Qadhi ‘Iyadh, pendapat as-shahih yang di pelopori oleh mayoritas Ulama mengarahkan tujuan sikap Nabi di atas pada ihtiyath (antisipasi) agar terhindar dari penyakit kusta19.
Kesimpulannya, kebijakan physical distancing dengan memandang ulasan yang tetera adalah wajib dita’ati secara mutlak baik dzahir ataupun bathin20.
Oleh: Redaksi
Refrensi:
- https://covid19.who.int.
- Al-Bukhari, Abu abdillah Muhammad bin ‘Ismail, Shahihul-Bukhori, III/45, cet. Dar Thauqin-Najah
- Syeikh Muhammad Hasan Hito, Al-Wajiz Fi Ushulit-Tasyri’ al-Islami, hal. 92
- Al-‘Aini, Badruddin, Umdatul Qori, hal. IX/67, Maktabah Syamilah
- ibid
- Al-Ghazali, Muhamamad bin Muhammad, al-Mustasyfa, II/392, cet. Daruz-Zahim
- Al-Anshari, Zakariya bin Yahya, Ghâyatul-Wushûl, hal. 159
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, Syarh Tanqhîhil-Fushûl, III/119
- Al-Baghdadi, Abdul –Mu’min bin Abdul-Haq, Taisîrul Wushûl ilâ Qawâidil-Ushûl, hal. 401
- Ibid
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, Ibnu Hajar, Fathul-Bârî, X/159
- al-Haitami, ِ Ahamd Syihabuddin, Ibn Hajar, Fatawa Ibn Hajar, V/325, cet. Darul Fikr – Beirut
- Op Cit
- Ar-Ru’aini, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad, Qurratul-‘Ain, hal. 19
- Op Cit
- Az-Zuhaili, Mushtafa Wahbah, al-Wajîz Fî Ushûlil-Fiqh, hal. 87, cet. Darul-fikr.
- Al-Ghazali, Muhamamad bin Muhammad, al-Mustasyfa, II/56
- Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdillah, al-Mantsûr fil-Qawaid, II/59
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, Ibnu Hajar, Fathul-Bârî, X/78
- Ba’alawi, Abdurrahman bin Muhammad bin Husein, Bughyatul-Mustarsyidîn, hal. 34