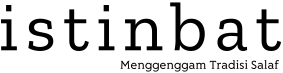Otoritas Fatwa di Zaman Sekarang
Islam adalah agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ dengan hukum-hukumnya yang telah terdokumentasikan secara rapi dalam kitab al-Quran, di samping sabda Nabi yang tak ubahnya saudara kembar bagi al-Quran dalam hal sama-sama memberi penjelasan tentang hukum Islam.
Sungguh akan terasa sangat mudah mengetahui ajaran Islam saat Nabi masih hidup berdampingan dengan penganutnya, sebagaimana seorang murid tidak akan kebingungan dalam belajar saat di temani guru yang setia mengajarinya, cukup bertanya saat tidak tahu, lalu dijawab dan selesailah urusan, beda halnya setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Namun kemurnian ajaran Islam akan tetap terjaga jika diemban oleh orang-orang pilihan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab tinggi dari satu masa ke masa yang lain.
As-Syekh Muhammad al-Khudhari Bik membagi tasyri’ (pengajaran syariat Islam) menjadi enam fase. Pertama, di masa hidup Nabi. Semua orang sepakat bahwa tindakan beliau menjadi landasan dan teladan bagi umat. Kedua, di era pembesar shahabat yang berakhir dengan selesainya kepemimpinan Khulafa’ur Rasyidun, empat shahabat Nabi yang menjadi khalifah pasca Rasulullah wafat. Ketiga, periode shahabat junior dan tabiin hingga abad pertama. Keempat, saat Fikih menjadi bagian dari disiplin ilmu dan bermunculannya pakar Fikih yang memegang kendali agama dan berakhir pada abad ketiga Hijriah. Kelima, masa di mana ilmu Fikih menjadi bahan perdebatan dalam rangka memperjelas masalah-masalah yang diterima dari para imam mazhab hingga muncullah karya-karya ilmiah yang tebal. Masa ini berahir bertepatan dengan runtuhnya Baghdad, berakhirnya dinasti Abbasiyah dan Tatar menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Keenam, masa taklid, mengikuti salafus shalih secara total, yaitu setelah runtuhnya Baghdad hingga sekarang.1
Pemberlakuan taklid bertujuan agar hukum Islam tidak sembarangan disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Sebab jika mengaca pada lima priode pertama, orang pada priode keenam sangat jauh dari kata setara dengan mereka secara kualitas. Pada abad kedua, banyak bermunculan pakar Fikih yang mampu membuat kaidah tersendiri dalam menggali hukum dari nash, lalu disusul oleh generasi yang mengkaji dan mengetahui metode imamnya dalam mencetuskan hukum. Dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan, apa yang bisa diperbuat oleh generasi setelah mereka? Sedangkan masalah terus berdatangan dan harus di tangani oleh ahlil ilmi atau Fakih (pakar Fikih, Hadis dan Tafsir).2
Lantas siapakah yang dikehendaki dengan Fakih yang notabenenya sebagai konsultan keagamaan dan permasalahan kehidupan? Dia adalah orang yang menguasai semua bab-bab Fikih dan mampu menjadikannya sebagai dalil untuk masalah-masalah lain yang belum tertulis.3 Dengan demikian, gelar ‘Fakih’ tidak bisa disandang oleh orang yang hanya menguasai pembahasan tertentu dalam fikih, seperti halnya bab haid saja atau dua bab lain.4 Tentunya, sulit menemukan orang dengan tipe demikian, sekalipun keberadaannya tidak mustahil.
Dalam menyikapi hal ini, Imam as-Subki telah memerinci tingkatan dan peran orang yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad mutlak menjadi tiga bagian. Pertama, ashhabul wujuh, yakni mereka yang mampu menggali hukum dari nash imamnya, al-Quran atau Hadis secara langsung menggunakan metode mazhab yang dianut. Kedua, orang di bawah tingkatan ashhabul wujuh namun pengetahuan Fikihnya sudah mewatak, menjaga dan mampu menjelasakan mazhabnya. Dua bagian pertama ini hampir tidak ada yang memperselisihkan dalam bolehnya mencetuskan fatwa.5 Ketiga, seseorang yang tidak mencapai kedua tingkatan ini, dia hanya menghafal permasalahan-permasalahan yang mudah dan rumit, namun tidak memiliki kemampuan menggali dalil-dalilnya. Orang yang berada pada tingkatan ini boleh untuk megeluarkan fatwa dalam masalah yang sudah ada nash tertulis dari imam yang diikuti, atau dalam masalah yang sudah diketahui masuk dalam dhabith, standar yang sudah dipermudah dalam mazhab, dan juga dalam kasus yang memiliki persamaan dengan kasus lain yang tidak perlu upaya keras untuk menyamakannya. Maka dari itulah orang ini bisa menjawab masalah-maslah yang baru, karena hampir tidak ada masalah yang belum ada nash dalam mazhab menurut Imam Haramain.6
Sedangakan orang yang masih belum sampai pada tingkatan tadi, tidak boleh memberikan hukum selain menggunakan fatwa tertulis dari imam yang dianutnya, sekalipun dia menemukan satu perbandingan masalah yang mirip dengan kejadian yang sedang dihadapinya.7
Oleh: Syukron Makmun
Referensi:
- As-Syaikh Muhammad al-Khudhari Bik, Tarikhut-Tasyri’ al-Islami, Darul Kutub al-Ilmiah, hal. 4
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Ba’alawi, Bughyatul Mustarsyidin, Maktabah Syamilah, hal. 389
- Ibid, 439
- Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi Al-Bakri, I’anatuth-Thalibin, Maktabah Imaratullah, hal. 214
- Abul-Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, al-Furuq, Maktabah Syamilah, II/185
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Adabul Fatwa, Darul Fikr, hal. 31
- Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Maktabah Syamilah, IV/296