NAHI MUNGKAR KEPADA WALI
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda;
إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ
“Sesungguhnya Allah berfirman: Barang siapa yang memusuhi kekasihku maka sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan padanya. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri padaku dengan ibadah-ibadah sunah sehingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku yang menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, pengelihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta padaku, pasti akan aku berikan. Jika dia meminta perlindungan padaku, pasti akan aku lindungi”.1
Hadis Qudsi di atas merupakan sebuah gambaran bahwa seorang wali sama sekali terlepas dari sifat kemanusiaannya dan tidak memiliki iradah (kehendak hati) yang ia gunakan untuk mengotrol dirinya2. Dipandang dari sini, sangatlah pantas jika ada beberapa wali melakukan sebuah tingkah yang tidak lazim dilakukan oleh manusia secara normal. Ada yang tidak bisa dinalar, seperti terbang, berjalan di atas air, dan lainnya. Ini disebut dengan al-Karamah. Ada pula diantara mereka yang melakukan sesuatu, yang secara zahir tidak sesuai dengan koridor syariat, seperti tidak salat, mencuri dan lain sebagainya. Dan ini yang akan penulis ungkap dalam tulisan ini.
Sepaham yang kami pelajari, sebuah prilaku yang secara zahir tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan oleh para wali setidaknya ada dua klasifikasi. Pertama, prilaku itu terjadi di luar sadar seorang wali. Ketidaksadaran seorang wali terhadap prilaku yang dia lakukan, muncul disebabkan terlalu tenggelam dalam memikirkan kebesaran Allah I. Dalam keadaan ini, ditinjau dari segi fikih, seorang wali sama seperti seorang yang sedang mabuk. Lisan dan tubuh yang dia gerakkan telah lepas dari kehendak hatinya. Sehingga seorang wali tidak akan mampu mengontrol diri sebagai seorang manusia. Bahkan, banyak diantara mereka mengeluarkan sebuah ungkapan yang secara zahir mengarah pada keyakinan ‘Manunggaling Kawulo Gusti’, atau dalam istilah tasawuf dikenal dengan sebutan al-Hulul wal Ittihad (menyatu dengan Tuhan), seperti yang terjadi pada Imam Ibnu Arabi, Imam Yazid al-Busthami, Imam Ibnul Faridl dan Sunan Lemah Abang (Syekh Siti Jenar). Semua yang mereka lakukan telah lepas dari hukum syariat. Keadaan inilah yang kita kenal dengan istilah Jadzab. Dan ini sesuai dengan pendapat Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam karyanya al-Fatawa al-Haditsiyah:
“Segala bentuk mabuk yang timbul disebabkan oleh sesuatu yang mubah, maka orang yang mabuk telah lepas dari hukum syariat. Dan diantara ulama yang berpegang teguh dengan pendapat ini adalah al-Quthb ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jailani”.3
Penyampaian Imam Ibnu Hajar di atas, memberikan kesimpulan bahwa syariat tidak berlaku bagi para wali ketika mereka terlepas dari sifat kemanusiaan yang mereka miliki.
Namun, Imam Izzuddin bin Abdissalam pernah menyampaikan, “Jika ada seorang wali yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka berhak untuk ditakzir”4. Alasan yang mendorong Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat seperti itu adalah ketidakmaksuman seorang wali. Maka dari itu, sangatlah pantas jika seorang wali ditakzir ketika secara zahir mengaku sebagai Tuhan.
Kedua, perilaku itu terjadi dalam keadaan masih sadar. Dalam beberapa waktu, memang ada beberapa wali yang melakukan sebuah aktivitas yang secara zahir menurut syariat tidak diperkenankan. Seperti minum khamr, mencuri dan lainnya. Keadaan ini pernah terjadi pada Imam Ibrahim al-Khawwash. Singkat cerita, setiap kali nama beliau terkenal di suatu tempat, maka dengan segera beliau pergi dari tempat tersebut demi menghindari syuhrah (terkenal) dan dampak buruknya. Bahkan demi menghindari hal tersebut, beliau sampai mencuri baju seorang putra raja. Pada Akhirnya beliau tertangkap dan dikeroyok oleh masyarakat setempat. Saat itulah beliau merasa senang dan berkata, “Seperti inilah makam (kedudukan di sisi Allah) menjadi baik. Setelah kejadian itu beliau terkenal dengan julukan al-Lashushiyah (si Pencuri).
Dari kejadian ini, ada sebagian ulama Fikih yang mengkritik dan menyalahkan secara total apa yang dilakukan oleh Ibrahim al-Khawwash. Namun tak sedikit pula dari mereka yang membenarkannya sebagaiamana ulama tasawuf.
Ketika ulama tasawuf dimintai tanggapan secara Fikih atas kritikan yang dilontarkan oleh kalangan ahli Fikih dalam kasus yang terjadi pada Imam Ibrahim al-Khawwash, mereka menanggapi bahwa di dalam fikih, seseorang diperbolehkan untuk menggunakan obat-obatan yang haram ketika dalam keadaan darurat. Seperti berobat menggunakan benda najis atau yang lainnya. Mengenai yang terjadi pada Imam Ibrahim al-Khawwash, sebenarnya beliau juga dalam keadaan darurat. Beliau melakukan keharaman tersebut untuk mengobati hatinya supaya tidak memiliki rasa suka untuk terkenal. Jika mengobati tubuh diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram, harusnya dalam mengobati hati juga sangat diperbolehkan. Karena hati lebih utama dibandingkan dengan tubuh5.
Dipahami dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa kalangan sufi ketika melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat dalam keadaan sadar, sebenarnya mereka melakukannya karena terpaksa atau darurat, bukan melakukan berdasarkan hawa nafsunya. Maka dari itu, jika kita lebih memperhatikan lagi, sejatinya alasan yang dilontarkan oleh kalangan sufi sebenarnya merupakan alasan yang abstrak (qalbiyah), tidak mungkin bisa kita lacak dengan mata zahir. Sedangkan kemampuan kita dalam memahami mata bathin sangatlah terbatas. Berdasarkan keterbatasan kita ini, jalan yang paling tepat untuk ditempuh ketika ada seorang wali yang nyeleneh adalah husnudz dzan (berbaik sangka) dan at-taslim (pasrah tanpa Tanya). Inilah jalan yang harus ditempuh oleh kalangan fuqaha dalam menghadapi sikap nyeleneh yang terjadi pada sebagian kalangan sufi atau para wali. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam fatwanya memastikan bahwa orang yang mengkritik kalangan sufi maka tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah I dan tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat.6
Imam al-Yafi’i memberikan arahan kepada kita prihal sikap yang harus dilakukan ketika mendengar ada wali melakukan hal-hal yang secara zahirnya tidak sesuai dengan syariat dengan tiga sikap. Pertama, tidak langsung percaya. Hingga bisa dipastikan bahwa hal itu memang benar-benar dilakuakan oleh seorang wali.
Kedua, setelah bisa dipastikan bahwa yang melakukan adalah seorang wali, maka harus mentakwilnya sesuai dengan pentakwilan ulama ahli ilmu zahir dan batin yang sudah makrifat kepada Allah I.
Ketiga, menyadari bahwa hal itu keluar dari para wali dalam keadaan tidak sadar diri (atau sadar tapi ada hikmah yang tersembunyi). Bahkan suudz dzan (berburuk sangka) kepada mereka merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah I.7
Berdasarkan dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa prilaku para wali itu ada dua, ada yang bisa diikuti oleh kita dan ada yang tidak bisa kita ikuti. Prilaku yang bisa kita ikuti adalah prilaku yang sesuai dengan syariat. Sedangkan prilaku para wali yang tidak sesuai dengan syariat, maka tugas kita adalah taslim tanpa menirukan prilaku tersebut. Wallahu A’lam
Oleh: Redaksi
Refrensi:
- Imam Muhammad bin Ismail bin Ishak al-Bukhori, Shahih al-Bukhori, hadis ke-6502
- Imam Abdullah bin Hijazi as-Syarqawi, Syarhul Hikam al-‘Athaiyah, al-Haramain, Indonesia, Hal:102.
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, DKI, Beirut, Hal:224.
- Imam Abu Sa’id al-Khadimi, Bariqah Mahmudiyah, Mauqi’ul Islam, IV/272.
- Imam Afifuddin Abdullah bin As’ad al-Yafi’I, Raudlur Rayahin, DKI, Beirut, Hal:404.
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, DKI, Beirut, Hal:95 dan 147.
- Imam Afifuddin Abdullah bin As’ad al-Yafi’I, Raudlur Rayahin, DKI, Beirut, Hal:406.
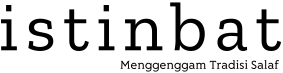










betul kali tuh, wali banyak yang aneh2 kelakuannya