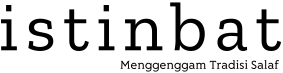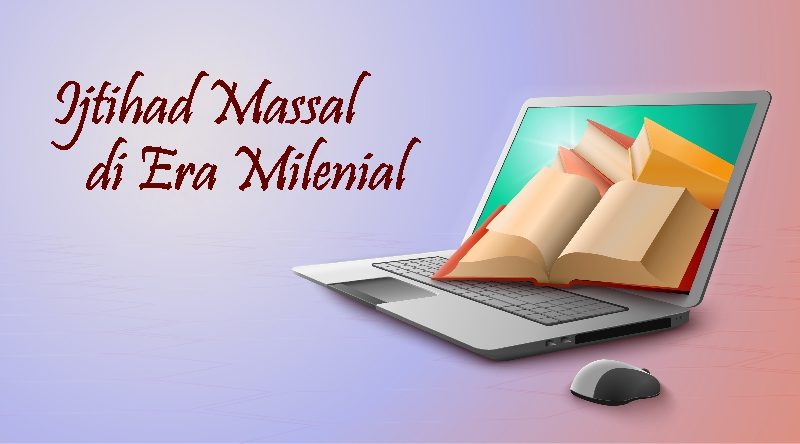Ijtihad Massal di Era Milenial
Kemajuan teknologi memiliki peran tersendiri dalam melahirkan problematika baru yang rumit. Berkaitan dengan agama, kasus yang hadir tentu menuntut orang yang mendalami hukum-hukumnya (ulama) untuk bersuara memberikan jawaban.
Jika ulama masa lalu tertuntut menuangkan hukum pada konteks yang ruang lingkupnya kecil, sekarang mereka dituntut untuk bersuara mengenai kasuistik skala lebar serta butuh melibatkan berbagai elemen dan komponen. Sehingga ulama masa kini tidak cukup menguasai dalil agama, namun juga harus mengerti arus globalisasi dan teknologi agar dalam mencetuskan hukum ia paham betul dengan problem yang menyapa.
Melihat kenyataan ini, beserta syarat-syarat menjadi mujtahid yang begitu rumit, tentu sangat sulit bagi ulama untuk mendapat stempel legal dalam mencetuskan hukum. Sehingga dengan beberapa pertimbangan, beberapa ulama Ushul Fikih kontemporer menawarkan aplikasi dalam berijtihad yang akrab dengan ijtihad jama’i (ijtihad massal).
Ijtihad jama’i adalah ijtihad yang lahir dari sekian ulama yang telah sampai pada derajat ijtihad juz’i (ijtihad parsial)1 setelah mereka mengetahui bersama kasus masalah, mendiskusikan dan menyepakati hukumnya.2
Maksud derajat ijtihad juz’i disini adalah kemampuan seorang ulama dalam menguasai dalil agama, seperti ushul, furu’ fiqh, tarikh tasyri’, khilafiyah dan lain-lain, namun mereka masih butuh orang lain untuk memastikan secara jelas problematika yang dikaji, seperti ekonom, ahli medis, ahli hukum negara dan semacamnya. Sebab, sangatlah absurd bagi satu orang menguasai betul (secara mendalam) segenap aspek ilmu agama plus juga ilmu modern untuk ia jadikan perangkat dalam berijtihad. Mudahnya, derajat ijtihad juz’i adalah kemampuan ulama di bidang Fikih, tapi belum menguasai kasus terkait tanpa melibatkan orang ahli di bidangnya.
Ijtihad model ini banyak digelar di beberapa kongres ulama dunia, khususnya di mukutamar-muktamar kajian keislaman yang akrab dihelat di abad ke-14 H, di mana para pemuka atau tokoh ulama bertemu dari belahan negara dan lintas mazhab. Muktamar tersebut turut meghadirkan spesialis sains, dokter, intelektual, advokat, ahli tata negara, akuntan, ekonom, ahli asuransi dan lain-lain.
Ijtihad jama’i memiliki nilai lebih dibanding ijtihad personal (al-ijtihad al-fardi) karena ia hadir melambangkan keselarasan opini tokoh-tokoh ahli di bidangnya, sehingga hukum yang dirumuskan lebih mendekati kebenaran daripada sekadar klaim seorang ulama saja. Di samping itu, keputusan ijtihad jama’i dicetuskan setelah melalui diskusi mendalam dan perdebatan panjang dengan mengkaji berbagai dalil-dalil agama, muqâranah madzâhib (komparasi mazhab) serta i’tibârul-mashlahah (peninjauan maslahat), di samping juga diperkuat dengan penuturan langsung pelaku kasus, yang dalam hal ini dihadiri oleh sepesialis spesifik modern.3
Mengenai dasar ijtihad jama’i, Syeikh Wahbah az-Zuhaili menyampaikan: “Konsensus yang lahir dari ijtihad jama’i harus memiliki dalil agama (mustanad syar’i) berupa nash atau maslahat yang bisa dirasakan umat secara umum, apalagi kita mengambil sikap al-Ghazali yang tidak menekankan keputusan Ijmak harus lahir dari kalangan ulama. Sehingga, non-ulama juga dipersilahkan ikut andil (dalam merumuskan kasus yang menjadi ahlinya) demi mencapai ijma’ yang final”.4 Bahkan, jika para mujtahid jama’i memerlukan spesialis tertentu yang non-Muslim demi memastikan kasuistik yang dihadapi, agama tidak melarang untuk melibatkanya.
Dengan model di muka, ijtihad jama’i lebih banyak diterima oleh berbagai kalangan, baik oknum atau komunitas ‘masyarakat’ Islam, karena ia hadir sebagai sikap serius dalam mengatasi berbagai masalah keagamaan dan melibatkan berbagai macam kalangan.5
Meski istilah ijtihad jama’i tampak baru di era millenial ini, namun bukan berarti ijtihad ini konsep abal-abal seperti ijtihad kaum liberal yang tak berdasar. Ada banyak inspirasi dan dalil yang mengarah, bahwa ijtihad jama’i adalah legal dan mendapat lampu hijau sejak zaman Nabi.
Imam at-Thabrani dalam al-Ausath menyebutkan, bahwa Sayyidina Ali pernah bertanya pada Nabi, “Ya Rasulullah, jika nanti ada masalah tidak ditemukan nash-nya (dalam Al Quran dan hadis) lantas apa yang kau perintakan pada kami?” Beliau menjawab, “Kau musyawarahkan masalah itu bersama ahli Fikih serta libatkan juga orang-orang yang ahli ibadah dari kaum mukminin, dan jangan kau menghukumi dengan pendapatmu semata”.
Dari inspirasi itulah, al-Imam al-Mawardi menegaskan pentingnya ijtihad jama’i dengan menggubah syair yang begitu indah di awal kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyah :
لاَ يُصْلِحُ النّاسَ فَوْضَى لاَ سَرَاةَ لَهُم * وَلاَ سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
“Manusia akan terus kacau tanpa ada ulama di antara mereka
Dan ulama pun juga tak dianggap jika pemimpinnya tak paham agama.”
Oleh: Firdaus Sholeh
Referensi:
- Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, Darul-Khair, II/352, cet. II
- Lebih lengkapnya baca kitab al’Ijtihad al jam’i karya Syeikh Abdul Majid as-Susah
- ibid
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Darul-Fikr, VIII/262, cet. IV
- Lop cit