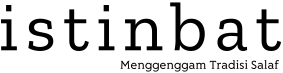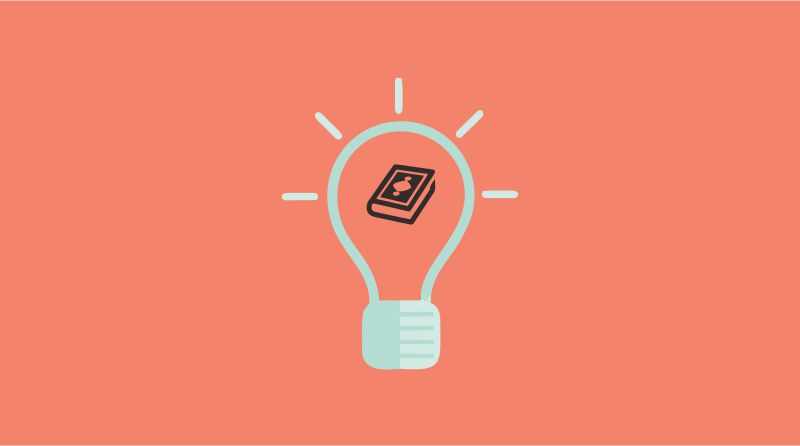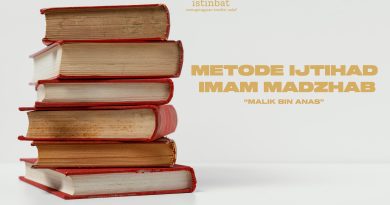METODE IJTIHAD IMAM MAZHAB (ABU HANIFAH)
Perkembangan hukum-hukum Fikih mulai dari awal kemunculan agama Islam sampai saat ini terpetak menjadi tiga fase:
Fase pertama terjadi semenjak Nabi Muhammad Diangkat Sebagai rasul. Beliau membawa dan menyampaikan risalah Islamiyah kepada semua makhluk yang secara garis besar mengandung tiga pokok ajaran; akidah, akhlak dan syari’at.
Fase kedua semenjak wafatnya Nabi, yaitu periode para sahabat. Munculnya hukum-hukum Fikih baru saat itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena pada masa sahabat pastinya banyak problematika yang belum pernah terjadi di saat Nabi masih hidup, Sehingga munculnya kejadian dan problematika baru ini menjadi pemicu para sahabat untuk menggali sendiri hukum-hukum fikih yang belum pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Fase ketiga adalah periode tabiin, tabiit-tabiin dan para imam mujtahid, yakni perkiraan abad kedua dan ketiga Hijriyah. Semakin meluasnya kekuasaan Islam dan bertambah banyaknya pemeluk agama Islam dari selain kalangan arab pada periode ini dengan kultur dan corak sosial yang beragam. Hal ini yang kemudian juga menjadi pemicu para mujtahid untuk menggali hukum-hukum baru yang belum pernah ada dimasa kenabian dan sahabat.
Berbicara tentang perkembangan Fikih pastinya tidak lepas dari Ushul Fikih sebagai ilmu dasar istinbatul-ahkam. Pada fase pertama, hanya Rasulullah yang mempunyai otoritas penuh dalam memutuskan hukum dan berfatwa. Fase kedua, yaitu periode Shahabat. Setelah Rasulullah wafat para Shahabat mulai berijtihad sendiri untuk memutuskan hukum problematika yang belum pernah disampaikan oleh Rasulullah. Berijtihad berarti mengerahkan kemampuan berfikir mereka secara totalitas dalam menggali hukum syariat. Pelegalan Ijtihad ini berdasarkan izin Rasulullah terhadap Shahabat Mu’adz bin Jabal saat beliau hendak diutus ke Yaman.[1]
Lanjut ke fase ketiga, yaitu periode tabi’in, tabiit-tabiin dan para imam mujtahid. Sebagaimana para sahabat, mereka juga menggali sendiri hukum-hukum yang belum pernah diputuskan oleh Rasulullah dan shahabat[2]. Namun, metode ijtihad yang dipakai oleh para imam mujtahid tidaklah sama. Mereka memiliki metode sendiri-sendiri dalam berijtihad, termasuk imam empat yang telah disepakati sampai sekarang; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad. Disini penulis akan membahas satu persatu metode ijtihad dari masing-masing empat mazhab tersebut dengan rinci. Yang insyaallah akan terselesaikan dengan empat artikel.
Manhaj Ijtihad Abu Hanifah
An-Nu’man bin Tsabit bin Zutha at-Taimi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Hanifah, Imam besar dalam Mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M di sebuah desa wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan (masa akhir Dinasti Umayah) dan meninggal di Baghdad tahun 150 H /767 M pada masa khalifah Abu Ja’far al-Mansur (masa awal Dinasti Abbasiyah), sehingga dalam kehidupannya, Abu Hanifah menjalani hidupnya di dua lingkungan sosial politik yang berbeda.
Beliau terkenal sebagai ulama yang memberikan porsi lebih terhadap ra’’yu (pemikiran) daripada kontekstualitas dalil dalam berijtihad. Hal ini, karena beliau hidup di Iraq yang kala itu merupakan kota besar yang maju. Kebudayaan yang beragam, politik, kajian keilmuan yang berkembang pesat dan juga banyaknya aliran disana seperti Ahlusunah, Muktazilah, Khawarij dan Syi’ah.
Dalam memutuskan suatu hukum Abu Hanifah mendahulukan apa yang ada dalam al-Quran. Jika tidak ada, maka selanjutnya beliau mengambilnya dari sunah Nabi. Apabila masih tidak ditemukan, maka beliau menggunakan pendapat para Shahabat baik yang sudah disepakati bersama (ijmak) atau tidak. Apabila masih tidak ada selanjutnya beliau mulai berijtihad sendiri. Adapun dalil yang beliau pakai sebagai dasar ijtihadnya tidaklah sama dengan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam mazhab yang lain. Selain al-Quran, Sunnah, Ijmak dan qiyas beliau juga punya dalil asal lain, yaitu pendapat Sahabat, istihsan dan ‘urf.[3]
Al-Quran dan Sunnah
Menurut Abu Hanifah al-Quran merupakan sumber utama dan tertinggi dalam penggalian hukum Fikih sebagaimana pendapat imam mazhab lainnya. Selain karena al-Quran adalah kalamullah, al-Quran juga merupakan kitab yang qath’iyyuts-tsubut, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya walaupun hanya satu huruf. Lain halnya dengan sunah yang bisa berstatus qath’iyyuts-tsubut apabila periwayatannya sampai pada tingkatan mutawatir. Jika tidak demikian, maka berstatus Dhanniyuts-tsubut, sebagaimana hadis ahad dan masyhur. Oleh karena itu, beliau menempatkan posisi sunnah di nomor dua setelah al-Quran.[4]
Aqwalush-Shahabah dan Ijma’
Abu Hanifah pernah berkata “Jika saya tidak menemukan (hukum) dalam kitab dan sunah, maka saya berpegang pada pendapat para Shahabat dan mengambil mana yang saya sukai serta meninggalkan yang lain, saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka, maka jika persoalan sampai pada Ibrahim, asy-Sya’bini, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said Ibnu Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.”[5] Perkataan ini menunjukkan bahwa beliau sangat berpegangan pada pendapat para Shahabat dan sebaliknya pada pendapat selain Shahabat.
Kenapa hanya pendapat shahabat? Demikian karena Shahabat adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah, menyaksikan secara langsung turunnya wahyu, mendapatkan futuh, ilmu serta pemahaman langsung dari lisan agung Rasulullah beserta pekerjaan dan akhlak beliau. Sehingga apa yang didapat dari mendengar dan menyaksikan secara langsung akan lain hasilnya dengan yang tidak secara langsung. Pendapat yang beliau ambil mencakup yang masih ikhtilaf ataupun yang sudah disepakati bersama (ijmak).
Ijmak adalah kesepakatan pendapat para mujtahid dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah pada suatu hukum syar’i. Baik kesepakatan ini terjadi di masa sahabat atau setelahnya sampai masa beliau. Penggunaan ijmak ini berpedoman pada hadis shahih riwayat Imam Ibnu Majah tentang ijmak.
Oleh: Fathur Rohman
Referensi :
[1] Al-Juwaini Abul-Ma’ali, Al-Burhan fi Ushulil-Fiqhi, Maktabah Syamilah II/505
[2] Khalaf Abdul Wahab, Ilmu Ushulil-Fiqhi, Maktabah Dakwah al-Islamiyah I/15, cet. VII
[3] Ibid.
[4] Ghawaji Wahbi Sulaiman, Abu Hanifah an-Nu’man, Dar al-Qalam Damasyqus, Hal. 135, Cet. VI
[5] Al-Bagdadi Ahmad bin Ali al-Khatib, Tarikh Bagdad
[6] Abdul Lathif, Syarh Manarul-Anwar, DKI, Hal. 260.
[7] Salim ‘Amr Abdul Mun’im, Al-Imam Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit, Dar adh-Dhiya’, Hal. 12, Cet. I
[8] Husain Hamid Hasan, Nazhariyatul Mashlahah, Hal. 585
[9] Al-Syarakhasyi, Ushulusy-Syarakhsyi, Lajnah Ihyaul Ma’arif an-Nu’maniyah, Hal. II/199-200
[10] Al-Hamdani Badr Fathi Hasan, al-‘Urfu wa al-‘Adah wa Adillatuhuma min al-Kitab wa as-Sunnah, DKI, Hal. 67