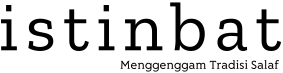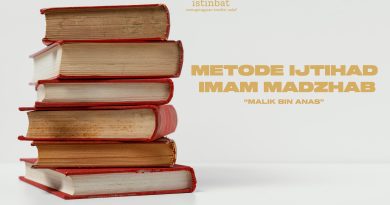Hadis Ahad: Antara Otoritas, kontroversi, dan Keabsahannya dalam Islam
Hadis merupakan rujukan utama umat Islam setelah al-Quran. Secara etimologi hadis berarti baru, kebalikan dari qadim yang bermakna terdahulu, secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad ﷺ baik berupa perkataan, pekejaan, ataupun ikrar (persetujuan).
Dari berbagai macam istilah terkait Hadis ada yang penting untuk dibahas, karena kerap menjadi sorotan dan memicu perdebatan panjang di kalangan para ulama, serta memiliki pengaruh urgen dalam penggalian hukum, yaitu hadis ahad, lawan dari hadis mutawatir.
Definisi Hadis Mutawatir dan Ahad
Hadis mutawatir adalah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang mana menurut kebiasaannya tidak mungkin sepakat dusta dalam hal-hal yang bisa ditangkap pleh panca indra. Sedangkan hadis ahad adalah: hadis yang rawinya tidak sampai pada derajat mutawatir. Banyaknya perawi dalam hadis mutawatir tidak memiliki batasan pasti, melainkan mengacu pada umumnya manusia. Meski sebagian ulama membatasi jumlahnya secara spesifik, namun hal itu telah dinilai daif oleh Syekh Zakariya al-Anshari.
READ MORE: Menjawab Tantangan Zaman: Pentingkah Ushul Fikih Hari Ini?
Ada beberapa hal yang perlu dibahas terkait hadis ahad, yaitu:
A. Tingkat kebenaran beritanya
Secara global terdapat dua pendapat mengenai kekuatan informasi yang diperoleh dari hadis ahad;
- Memberikan informasi taraf yakin (ilmu)
Pendapat ini diusung oleh sebagian ulama ahli Hadis. Argumen mereka, jika hadis ahad wajib diamalkan, maka semestinya informasi yang terkandung di dalamnya sudah sampai pada taraf yakin, sebab umat Islam dilarang mengikuti sesuatu yang masih belum mereka ketahui secara pasti. Namun pandangan ini, mendapat banyak kecaman dari para ulama. Menimbang, kesepakatan para ulama mengenai kewajiban mengamalkan hadis ahad tidak serta merta menunjukkan isi beritanya berada dalam taraf yakin. Sebab, kewajiban tersebut hanya berdasarkan pada aspek lahiriahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang menjadikannya layak dijadikan hujah dan wajib diamalkan.
Imam al-Ghazali turut berkomentar terkait pandangan ini. Menurut beliau, asumsi yang dibawa oleh ahli Hadis di atas itu mustahil, karena tidak ada dalil baik naqli maupun aqli yang menuntut hadis ahad wajib diamalkan. Oleh karenanya, kandungan berita dalam hadis ahad masih ada kemungkinan salah atau dusta. Sehingga tidak ada alasan untuk memastikan kebenaran beritanya. Dalam kitab al-Mustashfa al-Imam al-Ghazali menyatakan bahwa berita khabar ahad hanya sebatas dugaan kuat yang telah diketahui secara pasti (معلوم بالضرورة). Menurut beliau, istilah ilmu yang digunakan oleh para ulama hadis dalam hal ini kemungkinan besar yang dimaksud adalah dugaan kuat (Zhan), yang mana dalam mengamalkan suatu hadis cukup hanya berlandaskan dugaan kuat/ zhan saja.
2. Memberikan informasi bertaraf dzan/dugaan kuat
Pendapat ini diusung oleh mayoritas umat, baik dari kalangan ahli Fikih, ahli Ushul, maupun ahli . Hal ini berlandaskan dengan keberadaan hadis ahad yang levelnya di bawah taraf hadis mutawatir dan masih dikhawatirkan terjadinya salah dan lupa dari rawi, berbeda dengan hadis mutawatir, dengan banyaknya jumlah perawi yang secara urf dianggap tidak mungkin terjadi kebohongan terkordinir, membuatnya minim dari kemungkinan salah.
B. Penggunaan hadis ahad sebagai hujjah
Menjadikan hadis ahad sebagai hujjah yang wajib diamalkan masih menimbulkan khilafiyah di antara para ulama. Dalam hal ini, pandangan mereka terbagi menjadi dua golongan utama.
- Hadis ahad bisa dibuat hujjah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis ahad dihukumi wajib secara syariat dan jaiz secara akal, dengan artian ia termasuk hujjah dalam penetapan sebuah hukum.
Dalil yang menguatkan pendapat ini sudah jelas, baik dalam al-Quran, Hadis, ijmak ulama, maupun dalil secara logika. Namun secara global ada dua dalil yang menguatkan pendapat di atas, yaitu dalil aqli dan dalil naqli. Untuk Dalil naqli, dalam al-Quran disebutkan, contohnya:
“Tidaklah sepatutnya seluruh kaum mukmin berangkat juhad secara serempak, maka, mengapa tidak ada segolongan dari setiap kelompok diantara mereka yang berangkat untuk memperdalam agamadan agar memberi peringatan kepada kaum merka ketika sudah kembali kepada mereka, supaya mereka (kaumnya) dapat berhati-hati (dari kesalahan).” (QS. At-Taubah [9]:12)
Ayat ini mewajibkan adanya sebagian dari kaum muslimin yang fokus mempelajari agama untuk tujuan dakwah. Kewajiban yang hanya melibatkan segelintir orang ini mengindikasikan ajaran agama tidak harus disampaikan secara serentak oleh banyak orang, cukup beberapa perwakilan dari mereka. Sehingga dari ayat ini dapat mengindikasikan ajaran syariat yang dibawa oleh segelintir orang tetap wajib diamalkan.
Selain itu dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi pernah mengirim orang-orang khusus untuk menyebarkan ilmu syariat, seperti Sayidina Ali, Mu’adz bin Jabal, Attab bin Asaid, Dihyah dan lainya.
Pada dasarnya, sebuah berita ada kemungkinan benar dan salah. Namun dengan sifat adil yang dimiliki pemberi informasi dapat menjadikan informasinya lebih dekat dengan kebenaran, sebagaimana sifat fasik yang dimilikinya dapat mengubah informasi lebih dekat dengan kebohongan. Sehingga informasi yang didapat harus diamalkan ketika lebih unggul kebenarannya agar informasi itu dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, amal seseorang tetap dianggap sah tanpa harus berlandasan pada pengatahuan yang bertaraf yakin.
Namun tidak semua hadis ahad wajib diamalkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan hujjah yang berkonsekuensi wajib diamalkan, diantaranya:
- Orang yang meriwayatkan harus Islam, baligh, berakal, dan adil
- Sanadnya muttashil (bersambung) baik berupa hadis marfu’ (hadis yang disandarkan pada Nabi), hadis mauquf (hadis yang disandarkan pada Shahabat), atau hadis maqthu’ (hadis yang disandarkan pada tabiin.
- Tidak berlawanan dengan hadis yang lebih tsiqah
- Tidak ada illat yang merusak kualitas hadisnya. Seperti adanya teks yang dimanipulasi, atau kesalahan dalam riwayatnya.
Keempat syarat tersebut sudah disepakati oleh ulama, meskipun ada syarat lain yang masih diperselisihkan.
2. Tidak bisa dibuat hujjah
Imam al-Qasani, Abu Dawud dan kaum Rafidah, berpendapat hadis ahad tidak bisa dibuat hujah. Terdapat dua hal yang dijadikan pendukung dari pendapat ini. Pertama, akal menilai mustahil beribadah hanya berpedoman pada hadis ahad. Kedua, tidak ada dalil qath’I yang menuntut untuk mengamalkanya. Pendapat ini banyak menuai kritikan dari para ulama. Di antara alasan yang menolak pendapat ini adalah banyaknya riwayat yang menyatakan bahwa para Shahabat mengamalkan hadis ahad dalam banyak permasalahan[1], dan itu sudah menjadi konsensus/ ijmak dikalangan para Shahabat. Ini sudah cukup sebagai jawaban atas persepsi mereka di atas. Meskipun masih banyak dalil lain yang menolak pendapat mereka dan tidak perlu disebutkan seluruhnya, karena pendapat ini oleh al-Imam as-Sarakhasi dinilai sebagai pendapat yang tidak dianggap dalam kancah khilafiyah ulama.
Kesimpulannya. Khabar ahad dapat memberikan informasi yang bertaraf zhan menurut mayoritas ulama, dan bertaraf yakin menurut ahli hadis. Serta wajib diamalkan selaku dalil hukum yang dianggap dalam syariat Islam, ketika telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Meski ada yang menyatakan tidak wajib bahkan muhal untuk diamalkan, namun pendapat ini masih banyak menuai kritikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Oleh: Imaduddin
BACA JUGA: Awam dan Kewajibannya Terhadap Hukum Syariat
Referensi:
Syamsuddin Abul Khair as-Sakhawi, Fathul-Mughis, I/22
Zakaria al-Anshari, Ghayatul-Wusul fi Syarhi Lubbil-Ushul, 107
Abi Musthafa al-Baghdadi, Nuzhatul-Uqul Syarh Ghayatul-Wusul fi Syarhi Lubbil-Ushul, 221
As-Syairazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, at-Tabshirah fi Ushulil-Fiqh, I/299
As-Subki Taqiyyuddin Ali bin Abdul Kafi, al-Ibhaj fi Sayrhil-Minhaj, II/252
Imam al-Ghazali, al-Mankhul min Ta’liqatil-Ushul, I/341
Imam al-Ghazali, al-Mustashfa, 188
Syekh Muhammad Hasan Hito. Al-Wajiz, 99 dan 341-360
Al-Amidi Abul Hasan Sayiduddin Ali bin Abi Ali, Al-Ihkam fi Ushulil-Ahkam, II/69
Al-Bazdawi Fakhrul Islam Ali bin Muhammad, Ushulul-Bazdawi, I/154
Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini an-Naisaburi, al-Burhan fi Ushulil-Fiqh, I/388
As-Syairazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, at-Tabshirah fi Ushulil-Fiqh I/305
As- Sarakhasi Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, Ushulus-Sarakhasi, I/322