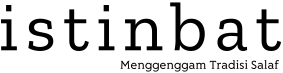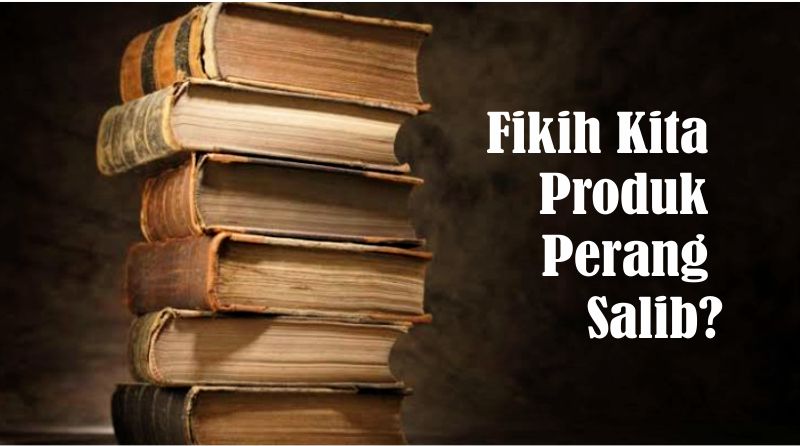Fikih Kita Produk Perang Salib?
“Andaikata orang-orang Islam hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia,” Demikianlah Sayid Muhammad mengatakan.[1]
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang belakangan ini dilontarkan oleh Imam Masjid Istiqlal, KH. Prof. Nasaruddin Umar. Melalui lisan beliau, narasi radikalisme ditubuh pesantren kembali digulirkan oleh Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT).
Melalui beliaulah muncul usulan agar pengajaran kitab fikih di pesantren dikaji ulang. Alasanya, kitab fikih yang diajarkan dipesantren hingga saat ini merupakan produk Perang Salib. Ia menganggap, materi yang ada tidak relevan dengan kondisi saat ini. Salah satunya, materi fikih tentang konsep negara.[2]
“Kitab-kitab fikih yang kita pelajari sebetulnya produk-produk, sebagian besar produk Perang Salib. Maka itu konsep kenegaraan itu masih ada Darus Silmi, negara Islam. Kalau bukan negara Islam, berarti Darul Harb, negara musuh,” kata Nasaruddin dalam diskusi di kantor BNPT, Jakarta, Rabu lalu (10/6/2020).
Ia menjelaskan, bahwa kitab fikih produk Perang Salib memuat tiga konsep negara. Yakni Darul Islam, Darul Harb (negara musuh), dan Darus Sulh (negara yang tidak menganut Islam, tetapi bersahabat dengan Islam). Menurutnya, bahwa tiga konsep negara tersebut sudah tidak tepat dengan kondisi saat ini. Bahkan ia melihat beberapa negara Islam yang ada justru mengalami kehancuran.
Pernyataan ini tentunya dinilai provokatif. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu penulis kritik. Meskipun sudah banyak tokoh yang menanggapinya, perlu kiranya penulis pertajam kritik yang sudah ada dengan beberapa tambahan pandangan.
Pertama, pernyataannya bahwa sebagian besar fikih yang kita pelajari adalah produk Perang Salib. Tanggapannya adalah fikih sudah ada sejak zaman nabi Muhammad ﷺ. Dalam kitabnya, Muhammad Hasan al-Hajwi memaparkan perkembangan fikih dalam empat bagian. Fase awal (fase thufuliah), yaitu dimulai sejak terutusnya baginda Nabi sampai beliau wafat. Fase kedua (fase syabab), yaitu dimulai di zaman khulafaur rosyidin sampai akhir abad kedua. Fase ketiga (fase kuhûlah), yaitu dari akhir abad kedua sampai akhir abad keempat. Fase terakhir (fase syaikhukhoh), yaitu dimulai setelah abad keempat sampai sekarang.[3]
Di fase pertama, sebagian besar fikih Islam terbentuk di masa sepuluh tahun setelah hijrah sampai wafatnya Nabi. Dengan wafatnya baginda Nabi, selesailah tarikhut tasyri’ al-islami, dan yang tersisa adalah tarikhul fiqh, yaitu pencabangan hukum (tafri’) dan penggalian hukum (istinbat) melalui metode ijtihad dari ushul yang di bawa oleh baginda Nabi. Begitulah fikih terus berkembang mengikuti perkembangan waqi’iyah yang terjadi di zamannya.
Dari sedikit pemaparan diatas, ungkapan profesor bahwa fikih Islam merupakan produk Perang Salib sudah terbantah. Karena kita tahu bahwa Perang Salib terjadi jauh hari setelah masa nubuwah, yaitu pada tahun 490 H sampai 670 H.
Kedua, pengkajian ulang fikih terkait formulasi ulama tentang dikotomi wilayah: Darul Islam (negara Islam) dan Darul Harbi (negara perang). Jika yang dimaksud produk Perang Salib adalah formulasi ini, maka tentunya terbantahkan pula pernyataan tersebut. Formulasi ini dirumuskan fuqaha melalui ijtihad mereka di abad kedua,[4] bukan era perang Salib. Meskipun, dalam merumuskan formulasi ini ulama juga mempertimbangkan fakta yang terjadi di lapangan yaitu suasana konflik dan perang.
Perlu penulis paparkan, pembagian ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan dunia dibawah hukum dua negara atau dua koalisi kekuasaan. Salah satunya mencakup negara Islam dibawah satu kekuasaan dan yang lain mencakup negara non-Islam dibawah satu kekuasaan juga. Pembagian ini dibuat dengan meninjau terpenuhinya syarat keamanan dan keselamatan masyarakat Muslim di negara mereka serta ada atau tidaknya ketakutan dan permusuhan di negara lain sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah. Atau dapat kita simpulkan bahwa perbedaan agama bukanlah poin dalam menentukan perbedaan wilayah ini. Titik poin penentuan ini adalah keamanan dan ketakutan.[5]
Pembagian wilayah juga dibuat untuk mempermudah ulama fikih dalam menentukan hukum bagi orang yang berada di wilayah mayoritas non-Muslim dengan mereka yang menetap di wilayah mayoritas Muslim, dan membedakan hukum orang yang berada di zona konflik dengan mereka yang berada di zona aman. Penjelasan hukum seperti ini sangat penting pada masa itu, khususnya bagi saudagar Muslim yang kerap kali pindah dari suatu wilayah ke wilayah lain, karena perbedaan konteks sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap perubahan hukum, termasuk aturan ibadah orang yang berada di zona aman dan zona musuh serta penerapan hudud bagi pelaku kriminal dan lain-lain.
Dari sekelumit pemaparan ini dapat kita pahami, apapun motivasi dari pernyataan profesor tidak dapat dibenarkan, termasuk motivasi untuk menghalau laju radikalisme di Indonesia. Karena pembagian ini tidak dimaksudkan sebagai dalil bahwa orang-orang Muslim boleh memerangi dan menginvasi wilayah musuh selagi masih ada orang-orang kafir yang tidak tunduk dan masuk Islam. Selain itu, antara radikalisme di Indonesia dan rumusan ulama di masa itu tidak ada kaitan sejarahnya. Indonesia dengan ulama di dalamnya justru akan menjadi penangkal radikalisme jika kedua istilah ini dipahami dengan benar oleh warga negaranya.
Akhiran, penulis mengutip pembenaran pemikiran terkait formulasi dikotomi wilayah ke dalam dua kelompok negara oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Pertama, kebutuhan orang-orang Muslim di awal urusan mereka pada penyatuan usaha dan pengawasan pondasi kekuatan mereka dalam menghadapi musuh dari luar. Hal ini dalam rangka menjaga eksistensi Islam di awal pembentukan negara Arab. Kedua, mendudukkan masalah fikih perihal relasi yang terjalin antara orang Muslim dan non-Muslim dan hubungan yang berkaitan dengan peperangan.[6]
Kedua hal itu tentunya tidak menafikan bahwa pembagian ini merupakan hasil ijtihad ulama yang berdasarkan dari penggalian dalil. Juga, bagian dari kekayaan intelektual yang patut untuk kita kaji dan hargai andaipun dimasa sekarang sudah dianggap tidak relevan.
Oleh: Abdul Basith
Referensi:
- As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-hasani al-Makki, Syariatullâh al-Khalidah, Darus-Syuruk, hal. 2
- CNN Indonesia | Rabu, 10/06/2020 18:54 WIB
- Muhammad al-Hasan al-Hajwi ats-Tsa’âlabi, al-Fasi, al-Fikrus Sâmi fi Tarikhil Fiqhi al-Islami, Darul Kutub al-Ilmiyah, I/59, Beirut, Lebanon
- Syekh Wahbah az-Zuhaili, Atsarul Harb fil-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah (Pengaruh Perang terhadap Fikih Islam: studi perbandingan), hal. 194-196, Darul Fikr, Damaskus, 1998 M.
- Syekh Wahbah az-Zuhaili, Atsarul Harb fil-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah (Pengaruh Perang
terhadap Fikih Islam: studi perbandingan), hal. 195, Darul Fikr, Damaskus, 1998 M. - Ibid