MENGAPA PINTU IJTIHAD HARUS DITUTUP ?
Prolog
Saat ini kajian Islam menemukan tantangan paling berat. Pasalnya, Islam yang telah dirumuskan ulama abad pertengahan dengan tingkat kehati-hatian tinggi, kapasitas keilmuan yang tidak diragukan dan kompeten dalam amaliyah berkehidupan semakin hari terus digerus. Mereka akrab menyebut dirinya dengan penggerak pembaruan Islam. Mulai dari pondasi teologi yang aksiomatis, metodologi al-Quran dan Sunah juga fikih aplikatif mereka bongkar habis-habisan. Dengan teori relevansi dan relatifitas, mereka berani melakukan itu semua.
Tentu apa yang mereka hasilkan tidak bisa disebut representasi Islam yang telah diwariskan Rasulullah. Sebab selain tampilan yang menyalahi aturan main, referensi yang tidak akurat dan tentu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Dengan begitu, penulis tertarik untuk menguraikan tema ijtihad dan semua hal yang berkaitan, dengan berpijakan pada referensi yang akurat sebagai perbandingan kepada umat Islam. Sehingga gerakan atau pemikiran yang sedang berkembang bisa diimbangi, atau bisa dipatahkan. Selamat membaca!
Pintu Ijtihad
Mayoritas ulama satu pandangan bahwa syarat mujtahid mutlak tidak akan terpenuhi pada sesorang ulama abad keempat hijriyah. Sementara seseorang yang mengaku telah memenuhi syarat-syarat itu, maka ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama, pengakuan itu hanya mengada-ada, sedangkan kemungkinan kedua hukum fardhu kifayah mengenai ijtihad bukan berarti orang mukallaf wajib terjun secara praktis dalam ijtihad, akan tetapi mereka berkewajiban memenuhi syarat-syarat ijtihad.[1]
Imam al-Ghozali menyatakan “Syarat-syarat ijtihad yang harus dimiliki oleh qadi itu sudah sampai taraf udzur untuk dapat dipenuhi”. Bahkan dalam kitab al–Inshaf ditegaskan bahwa mujtahid mutlak sudah tidak ada. Dalam hal ini pernah Imam Muhammad bin Jarîr ath-Thobri mengaku telah sampai pada pangkat mujtahid mutlak. Akan tetapi ulama tidak sepakat dengan pengakuan itu, padahal tidak ada yang meragukan lagi kapasitas keilmuan ath-Thobri yang telah mendunia, bahkan beliau sendiri termasuk ulama abad keempat. Kemudian al-Qarafi menyimpulkan bahwa tidak mungkin syarat-syarat ijtihad mutlak dapat dipenuhi pada masa setelah abad keempat.
Pengertian Ijtihad
Menurut istilah yang disepakati ulama Ushul Fikih, Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan berpikir terhadap dalil-dalil syariat untuk menelurkan hukum-hukum syariat. Berdasarkan definisi ini ulama mengatakan bahwa wewenang ijtihad hanya diperuntukkan kepada orang bidang dalam fikih, kompeten dalam sumber-sumber dalil, dan cakap dalam metodologi istinbat.
Lebih rinci, dalam kitab Ma’alimul Ushûl ‘inda Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah disebutkan kriteria sesorang yang boleh terjun dalam ijtihad mutlak, yaitu:[2]
Pertama, pakar dalam al-Quran, Sunah, ijma’, qiyas, istishab, dan dalil-dalil serupa yang dibutuhkan dalam proses ijtihad. Selain itu harus mengetahui maqashidus syari’ah, rinciannya adalah mengetahui seluk beluk dalil-dalil hukum dalam al-Quran dan Sunah, nâsikh dan mansûkh, posisi ijma’ dan khilaf dan mengetahui hadis yang sahih dari yang daif. Berkenaan poin ini Imam Hisyam bin Abdullah ar-Razi mengatakan “Seseorang yang tidak mengetahui posisi ijma’ dan khilaf ulama bukanlah fakih”.[3] Lebih mengerikan lagi apa yang dikatakan Imam ‘Atha’ bahwa tidak patut berfatwa seseorang yang tidak ahli dalam ikhtilaful ulama. Sebab sangat mungkin dia akan menolak pendapat yang sebenarnya lebih kredibel dibanding pendapat yang ada padanya. Lebih ganas Imam Qatadah menyatakan “Siapa yang tidak pakar dalam ikhtilaful ulama, jangan sekali-kali mendekatkan hidungnya kepada fikih[4]” Kedua, pengetahuan gramatika Arab yang dapat membantunya untuk memahami teks. Ketiga, kapasitas tinggi dalam kategori teks, mulai ‘am dan khash, mutlaq dan muqayyad, nash, zâhir dan mu’awwal, mujmal dan mubayyan, manthûq dan mafhûm, serta muhkam dan mutasyâbih. Keempat, serius dan amanah dalam berusaha mencetuskan hukum. Kelima, sandaran dalil yang kuat. Keenam, memahami situasi dan kondisi zaman dan lokasi di mana di berijtihad.
Ijtihad Kontemporer
Tentu sangat berbeda dengan proses ijtihad seseorang yang mengaku sampai pada kapasitas ijtihad. Mereka dengan tampa malu memproklamirkan kemampuan dalam ijtidah dengan komponen dan instrumen yang tidak memadai. Ijtihad kacangan yang dilakukan oleh kontemporer lebih tepat perspektif Imam Ibnul Qayyim adalah perkiraan dan tebakan secara sembrono dalam menelaah nash-nash teks dan metodologi pencetusan hukum. Imbasnya, pelaku ijtihad model seperti akan terjerumus dalam ar-ra’yul-madzmûm.
Bisa diperhatikan penyataan Imam as-Syafi’i (w. 204 H) yang mengatakan bahwa untuk memunculkan pendapat harus betul-betul matang, kondisi akal memadai, bisa membedakan mana teks yang serupa dan telah meneliti konteks yang sedang berlaku.
Epilog
Bukan tampa alasan sikap ulama untuk menutup pintu ijtihad sekitar abad keempat hijriyah. Menurut hemat penulis jika ijtihad tetap dibuka lebar-lebar setidaknya akan berakibat dua hal besar. Pertama, perpecahan umat Islam. Umat akan bingung siapa yang akan diikuti, sementara orang yang mengaku mujtahid tidak ahli dalam ijtihad. Kedua, kaburnya tatanan keilmuan umat. Sebab, ketika seseorang diberikan wewenang berijtihad, secara otomatis dia akan menuliskan metodologi ijtihadnya. Orang yang lain juga demikian dan seterusnya. Akibatnya akan terjadi ketidakjelasan ilmu keislaman.
Maka, hal terbaik adalah mengikuti ulama yang telah terbukti kepakaran dan kapasitas keilmua mereka. Tidak mempunyai kepentingan terselebung dan istikamah dalam rel-rel syariat.
Oleh: Redaksi Istinbat
[1] Anwârul-Buruq fi Anwâ’il Furûq II/188
[2] Ma’alimul- Ushûl ‘Inda Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah, 464
[3] Al-Khulashah fi Asbabi Ikhtilafil Fuqaha’, I/86
[4] Ibid
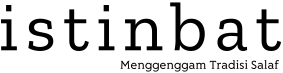










Pingback: Menjawab Tantangan Zaman: Pentingkah Ushul Fikih Hari Ini? - Istinbat