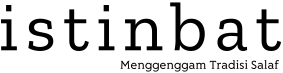Dinamika Feodalisme dalam Pesantren (Part I)
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, khususnya di tanah Jawa. Namun, akhir-akhir ini pesantren tak henti-hentinya menjadi sorotan dengan celah sedikit apapun, salah satunya adalah tuduhan adanya sistem feodalisme yang dianggap jauh dari nilai-nilai agama. Bermula dari banyaknya konten atau video yang beredar membahas praktik yang mengesankan nilai tidak biasa, seperti kiai memiliki otoritas penuh dalam lingkup kehidupan pesantren, berlebihan dalam menghormati kiai, mencium tangan bahkan kakinya, praktik tabaruk dan beragam hal yang lain.
Sehingga dari sini banyak yang mudah memvonis adanya terapan feodalisme dalam lini ajaran pesantren. So, apakah benar pesantren menerapkan feodalisme ataukah hanya sekedar tuduhan belaka? Dan apakah praktik mencium tangan, kaki dan lainnya dibenarkan secara agama? Mari kita bahas!
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, di mana penguasa (biasanya bangsawan atau raja) memiliki kekuasaan penuh atas bawahannya. Sekilas, struktural pesantren terlihat sama dengan sistem feodalisme. Akan tetapi, ketika kita teliti lagi, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara keduanya.
Feodalisme merupakan sistem sosial yang muncul di Eropa pada abad pertengahan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Istilah feodalisme sendiri baru dikenal pada abad ke-16 di Prancis. Sistem ini menjadi solusi untuk menata kembali ketertiban dan keamanan lokal setelah kemunduran otoritas pusat[1]. Feodalisme memiliki ciri-ciri yang bisa kita tangkap seperti hierarki[2], ketergantungan pada pemimpin, dan otoritas absolut seperti mewariskan kekuasaan kepada keturunannya.
Dalam struktural pesantren memang terdapat hierarki yang terbilang unik, akan tetapi jauh berbeda dengan sistem feodalisme yang berbasis pada kekuasaan dan keterpaksaan. Dalam pesantren, hubungan antara kiai dan santri lebih bersifat mendidik dan membimbing, bukan menindas atau mengancam. Tidak ada unsur paksaan atau ancaman dalam menunaikan perintah kiai, melainkan kesadaran dan kesediaan santri untuk belajar dan mengembangkan diri. Hal ini membuat pesantren menjadi lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan spiritual dan intelektual, bukan pada bisnis, kekuasaan atau dominasi.
Kiai memiliki otoritas yang tinggi dalam mendidik santri, tetapi bukan dalam bentuk kekuasaan absolut. Sebagai guru agama, kiai memiliki peran yang lebih luas daripada orang tua, karena tidak hanya mendidik anak dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam urusan akhirat. Orang tua memiliki hak atas anaknya karena peran mereka dalam melahirkan dan membesarkan, namun peran mereka hanya sebatas kehidupan dunia yang fana saja. Bedahalnya dengan kiai atau guru agama memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk karakter dan spiritualitas santri dalam mengantarkan ke kehidupan yang kekal kelak di akhirat, sebagaimana keterangan Imam al-Ghazali dalam salah satu karangan monumentalnya[3].
Baca Juga: Nderek Guru Dengan Bijak
Oleh karena itu, Syekh Muhammad as-Safaraini dalam kitabnya mengatakan:
يَنبَغِي اِحْتِرَامُ ٱلْمُعَلِّمِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلشَّيْخُ وَتَوْقِيرُهُ وَٱلتَّوَاضُعُ لَهُ، وَكَلَامُ ٱلْعُلَمَاءِ فِي ذَٰلِكَ مَعْرُوفٌ. وَذَكَرَ بَعْضُ ٱلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ حَقَّهُ مُؤَكَّدٌ مِنْ حَقِّ ٱلْوَالِدِ، لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِتَحْصِيلِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ، وَٱلْأَبُ سَبَبٌ لِلحُصُولِ عَلَى ٱلْحَيَاةِ ٱلْفَانِيَةِ، فَعَلَىٰ هَذَا تَجِبُ طَاعَتُهُ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ. قَالَ فِي ٱلْآدَابِ ٱلْكُبْرَىٰ: وَأَظُنُّهُ يَعْنِي بَعْضَ ٱلشَّافِعِيَّةِ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ. قَالَ: وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ ٱلْعِلْمِ، لَا مُطْلَقًا. اِنْتَهَىٰ
“Seyogyanya bagi seorang murid untuk menghormati guru agamanya (syekh), memuliakannya, tunduk dan bersikap rendah hati padanya sebagaimana komentar-komentar ulama yang sudah maklum. Sebagian kalangan Mazhab Syafiiyah mengatakan bahwa haknya guru (syekh) lebih besar dari pada hak orang tua kepada anaknya. Sebab orang tua hanya mengantarkan ke kehidupan yang fana, sedangkan seorang guru menjadi sebab dalam mengantarkannya ke kehidupan yang abadi (akhirat). Sehingga wajib bagi sang murid untuk mentati gurunya dan haram baginya untuk tidak patuh padanya. Pengarang kitab al-Adab al-Kubra mengatakan: ‘Aku menyangka perintah yang dimaksud oleh sebagian kalangan Syafiiyah adalah perintah kaitannya dengan keilmuan bukan mutlak.’”[4].
Sehingga, santri atau murid berkewajiban untuk memenuhi amanah atau perintah dari gurunya, terlebih jika perintah itu berupa didikan dari sang guru atau yang berkaitan dengan keilmuan dan masa depannya. Hal ini tidak lain sebab ilmu pengetahuan dan didikan yang diperoleh dari guru memiliki nilai yang sangat besar yang tidak dapat dibandingkan dengan apa pun yang dapat diberikan sebagai balasan. Oleh karena itu, memenuhi perintah guru menjadi kewajiban bagi santri sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas ilmu yang telah diperoleh.
Selain itu hierarki juga terdapat pada hubungan orang tua dan anak. Hierarki atau otoritas ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama. Orang tua memiliki peran penting dalam membawa anak ke dunia ini, sehingga anak memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah orang tua, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama[5].
Menaati orang tua bukan hanya sebagai bentuk rasa hormat, tetapi juga sebagai menunjukkan rasa syukur dan penghargaan atas peran orang tua dalam hidup mereka. Sehingga, ketika otoritas orang tua terhadap anak bukan atas dasar hierarki feodalisme, lantas bagaimana dengan otoritas kiai terhadap santrinya?
Dari sini, bisa kita simpulkan otoritas kiai dalam mendidik santri bukanlah berdasarkan hierarki feodalisme, melainkan otoritas keilmuan dan spiritual yang bertujuan untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak baik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat oknum-oknum yang memang memanfaatkan pesantren sebagai ladang bisinis atau sekadar kekuasaan saja. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mulia dapat ternodai oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan otoritasnya. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi kasus-kasus penyimpangan dengan objektif, tidak menyalahkan lembaga pesantren secara keseluruhan, tetapi menyalahkan oknum yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemuliaan dan integritas pesantren khususnya yang telah memliki peran penting di negeri ini, sekian.
Praktik mencium tangan, kaki dan lainnya Lanjut part II
Baca juga: MEMBIDIK SOSOK PEMIMPIN IDEAL
Achmad Qoffal/IstinbaT
[1] Buku Sejarah Lengkap Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M (2002) oleh Alfi Arifian, hlm 103.
[2] urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hierarki)
[3] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya Ulumiddin I/60, Maktabah Syamilah
[4] Syamsuddin Abul Aun Muhammad bin Ahmad as-Safaraini al-Hanbali, Ghidha’ul-Lubab fi Syarhi Manzhumatil Adab I/390, Maktabah Syamilah
[5] Taqiyyudin Utsman bin Abdurrahman (Ibnu Shalah), Fatawa Ibnus-Shalah I/201, (Turats)