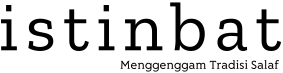KAMUFLASE ANALOGI NIKAH LINTAS AGAMA: Menelaah Pemikiran Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar
Nikah merupakan sebuah ibadah jika diniati karena Allah Di samping itu nikah berfungsi untuk menjaga keturunan, mengeluarkan sperma yang jika ditahan membahayakan dan memenuhi kebutuhan birahi serta biologis.[1] Dalam pandangan Islam, tidak sembarang wanita bisa dijadikan istri. Perempuan non muslim tidak mendapat legitimasi untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, kecuali mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Itu pun masih bersyarat.
Penyelewengan
Akan tetapi, ada saja sebagian pemikir Islam yang menyimpang lalu menyusupkan paham yang keluar dari suara konsensus ulama, sehingga paham semacam ini sangat meresahkan umat. Ambil contoh, Rasyid Ridha menawarkan statemen menikahi non-Muslim yang beragama Hindu, Budha dan sesamanya mendapat legitimasi dari agama.
Dalam menjustifikasi statemen ini Rasyid Ridha melakukan metode analogi dan berbagai distorsi. Awalnya, saat dia menginterpretasi ayat 221 surah al-Baqarah yang menyatakan bahwa Allah melarang umat Islam untuk menikahi orang kafir Musyrik, sedang pada ayat 05 dari surah al-Maidah dengan tegas, katanya, Allah memperbolehkan menikahi ahlul kitab, setelah itu, Rasyid Ridha menganologikan Majusi pada ahlul kitab karena memiliki syubhah minal kitab.
Untuk mengukuhkan ini, Rasyid Ridha mengutip pendapat Abdul Qdir al Baghdadi yang mengatakan bahwa, Majusi mengakui kenabian Zaradusytus yang menerima wahyu dari Allah yang tentu memiliki tuntunan kitab suci.[2] Karena kurun waktu yang sangat lama pengikutnya (Majusi) menyimpang hingga pada akhirnya menyembah api. Dengan demikian, Majusi masuk dalam kategori kelompok yang memiliki syubhah minal kitab. Lebih tegas lagi, Rasyid Ridha menyatakan bahwa Imam ats-Tsaur juga berpendapat sedemikian rupa.
Sama dengan Majusi adalah agama Hindu dan Budha yang memiliki tuntunan kitab suci. Dalam memperkokoh analogi pasaran ini, Rasyid Ridla menyodorkan ayat al- Quran yang artinya: ‘’Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.’’(QS. Ath-Thûr, (35): 24). Jika begitu adanya, tentu kitab yang menjadi tuntunan hidup dua agama ini dan, sesamanya merupakan kitab samawi yang dibawa oleh seorang utusan.
Bila Rasyid Ridha dihadapkan dengan sebuah kaidah al-ashlu fin-nikah at- tahrim, ia melakukan pendekatan pada surah an-Nisa’: 23-24 yang menjelaskan beberapa orang yang haram dinikahi dengan menitikberatkan pada pengecualiannya, lalu berkesimpulan, bahwa kaidah tersebut tidak berlaku lagi. Alasannya, setelah ayat ini turun, Allah menurunkan ayat dalam surah al-Baqarah dan an-Nisa’ di atas hingga kunklusinya pun kembali seperti apa yang ada di muka, ahlul kitab diperbolehkan dinikahi. Dan, yang memiliki syubhah minal kitab sama hukumnya.
Adapun mengenai Hadis yang berbunyi:
سنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، غَيْرَ آكِلِي ذَبَائِهِمْ وَلَا نَاكِجِي نِسَائِهِمْ
“Berlakukanlah mereka (Majusi) seperti kalian memperlakukan Ahlul Kitab, selain memakan sembelihan dan menikahi wanita-wanitanya.” (HR. Imam Malik).
Dia mengatakan, bahwa pengecualian yang ada dalam Hadis tersebut tidak benar menurut perspektif para pakar Hadis yang kredibel. Memang, katanya, para pakar Fikih mengakui pengecualian dalam Hadis ini dan diberlakukan dalam tatanan Fikih. Tetapi, lanjutnya, kita harus memprioritaskan peranan pakar Hadis dalam masalah ini.
Rasyid melanjutkan, al-Quran juga tidak tegas menjelaskan pernikahan dengan non-Islam selain Ahlul Kitab dan musyrik Arab. Karenanya, Majusi memiliki porsi hukum berbeda dari keduanya. Demikian itu, katanya, dalam banyak ayat, Allah selalu menjadikan masing-masing kelompok ini sebagai sekte yang berbeda. Ambil contoh surah al-Bayyinah: 01 dan al-Hajj: 17. Hanya saja, Majusi dalam masalah ini lebih mendekati pada ahlul kitab karena memiliki syubhah minal kitab, pungkasnya.[3]
Tanggapan
Untuk menanggapi statemen Rasyid Ridha di muka, perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa syarat hukum asal (Musyabbah bih) analogi itu harus merupakan hukum konsensus di kalangan ulama.[4] Sedangkan hukum asal dari menikahi ahlul kitab di sini ulama masih silang pendapat. Terbukti, Ibnu Umar dalam masalah ini mengatakan bahwa segala bentuk kemusyrikan menyebabkan dilarangnya menikah.[5] jika demikian, maka penganalogian kasus ini tidak dapat dibenarkan.
Hukum ahlul kitab ini saja ulama masih bersilang pendapat, apalagi ketika ditarik pada Majusi yang memang tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti demikian, sedangkan pernyataan Rasyid Ridla yang mengatakan bahwa Imam ats-Tsauri berpendapat seperti pendapatnya juga tidak benar. Lebih pasnya dia hanya memanipulasi pendapat orang saja, sebab, jika kita telisik dalam beberapa literatur klasik, disebutkan bahwa ast-Tsaur berpendapat Majusi disamakan dengan ahlul kitab dalam pemungutan Jizyah,bukan pernikahan.[6]
Dengan demikian, analogi yang ditawarkan oleh Rasyid Ridha penuh manipulasi, selain itu, bukti yang memperkuat bahwa kitab suci orang Hindu dan Budha merupakan kitab samawi juga tidak ada titik jelas. Dalam hal ini dia hanya melakukan pendekatan dari ayat al-Quran yang tidak ditopang dengan data historis yang akurat, sehingga, konklusi yang ditawarkannya pun rapuh dan tidak berdasar. Allah A’lamu bi tahqiqil waqi’. Bersambung!
Oleh: Redaksi Istinbat
[1] Muhammad Khatib asy-Syirbini, Mughnil Muhtâj ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhil Minhaj, III/123, versi Maktabah Syamilah.
[2] Abu Manshûr Abdul Qahir bin Thâhir al-Baidâdî, al-Farqu bainal-Firaq, 279, versi Maktabah Syamilah.
[3] Rosyid Ridla, Tafsir al-Manar, VI/150-161, versi Maktabah Syamilah.
[4] Syaikhul Islam Abū Yahya Zakariya al-Anshari, Châyatul-Wushûl Syarh lubbil-Ushûl, 111, al-Haramain.
[5] Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthûbî, al-Jami’ lî-Ahkâmil Qur’an, III/64, versi Maktabah Syamilah
[6] Abū Amar Yūsuf bin Abdullah bin Muhammad al-Qurthûbi, at-Tamhid lima fil-Muwaththa minal Ma’anî wal- Asânīd, II/118, versi Maktabah Syamilah.