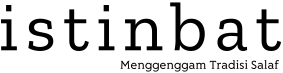Pemanfaatan Sebanding dengan Penjaminan
Prolog
Manusia sebagai makhluk sosial sangat erat kaitannya dengan saling menjalin hubungan dengan orang lain dalam menapaki hidup sehari-harinya. Hubungan antara satu dengan yang lain ini memiliki peran yang sangat vital dan tidak bisa dipisahkan, karena terputusnya perjalanan hidup ini akan terasa pahit dan hambar. Untuk membangun dan menyempurnakan hubungan sosial agar terjaga dan tertata dengan rapi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam keberlangsungan hidupnya, syariat datang dengan melegimitasi beberapa akad, seperti akad jual beli, akad gadai, akad bagi hasil dan akad-akad yang lain. Kemudian, syariat juga membentuk aturan-aturan tertentu untuk menghindari penyelewengan dan memberikan solusi ketika terjadi cekcok dalam mengaplikasikan akad-akad tersebut. Misalnya, ketika penjual meminta ganti rugi pada pembeli karena telah memakai barang pembeliannya yang dikembalikan sebab cacat. Maka untuk menyikapi konflik ini, syariat datang memberikan solusi kaidah secara umum yang juga bisa memberikan jawaban pada permasalahan-permasalah lain yang juga serupa subtansinya. Kaidah tersebut adalah:
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
“Pemanfaatan output merupakan imbalan atas adanya penjaminan.”
Dalil Kaidah
Redaksi kaidah ini, al-kharaj bidh-dhaman, diambil dari penggalan sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam asy-Syafii, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Berikut teks lengkap hadisnya:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ “أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)[1]
Diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya suatu ketika ada seseorang membeli budak dan memanfaatkannya, tetapi setelah itu ia menemukan aib dari budak tersebut. Pada akhirnya, ia mengembalikannya pada pihak penjual. Namun, pihak penjual tidak terima seraya mengadu pada Rasulullah, “Ya Rasulullah, dia telah menggunakan budakku.” Rasulullah menimpalinya, “Al-kharaj bidh-dhaman.”
Dalam hadis ini, penjual menyetujui atas adanya pengembalian budak yang sudah dijualnya karena adanya cacat. Akan tetapi, ia menuntut pembayaran upah sebagai kompensasi ganti rugi atas pemanfaatan budak tersebut selama berada di tangan pembeli. Rasulullah menolak tuntutannya dan menyatakan bahwa output dari budak tersebut (berupa jasanya yang diambil oleh pembeli) adalah legal karena ia memanfaatkanya atas dasar kompensasi dari tanggung jawabnya sebagai pemiliknya (dhaman) pada saat itu, meskipun pada akhirnya ternyata jual beli dibatalkan dan budak dikembalikan kepada penjual. Di antara tanggung jawab yang dibebankan kepada pembeli dari budak tersebut adalah memberi makan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh budaknya dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk kepentingan budaknya sehari-hari.
Pengertian Kaidah
Dalam khazanah hukum Islam, kata kharaj sering kali dihubungkan dengan urusan pemerintahan. Kharaj dalam kontek ini biasa dimaknai sebagai cukai hasil tanah dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat non-Muslim. Praktik ini kali pertama diprakarsai oleh Sayidina Umar terhadap lahan pertanian dengan kriteria-kriteria spesifik yang diperolehnya akibat perluasan wilayah Islam.
Berbeda dengan pengertian kharraj dalam kaidah ini. Kata ini memiliki arti output dari suatu pembelian, baik berupa barang atau manfaat. Dalam hal ini, ia diistilahkan dengan ghallah atau qira’ . Contohnya seperti buah yang dihasilkan oleh pohon, susu yang dihasilkan oleh hewan, keuntungan berupa uang dari deposito, imbalan sewa berupa uang dari menyewakan rumah, pembajakan sawah yang dihasilkan dari seekor kerbau dan penggunaan mobil sebagai pemanfaatan yang dihasilkan dari sebuah mobil.[2]
Selanjutnya, kata dhaman dalam literatur fikih memiliki makna yang amat beragam tergantung bab yang menjadi titik pembahasan. Adapun pengertian dhaman dalam kaidah ini adalah penjagaan dari kerusakan atau kehilangan yang berada di bawah otoritas pembeli. Andai barang tersebut rusak atau hilang maka si pembeli yang menjadi penanggung jawab atas hal tersebut[3].
Pada intinya, pengertian secara menyeluruh dari kaidah ini adalah bahwa output dari suatu pembelian baik berupa manfaat atau barang adalah milik si pembeli karena ia sebagai penanggung jawab atas barang tersebut. Andaikan ada apa-apa dengan barang tersebut maka ia menjadi penanggung jawab atas risikonya. Jadi pada hakikatnya, output ini diposisikan sebagai bentuk imbalan atas adanya tanggung jawab. Seseorang yang siap menanggung risiko atas pembelian andaikan terjadi kerugian, maka ketika untung ia juga berhak atas hasil keuntungannya. Kaidah ini nyaris senada dengan kaidah lain yang berupa:
الْغنَمُ بِالْغُرْمِ
Penerapan Kaidah
Kaidah ini bisa dikatakan berbeda dengan kaidah-kaidah fikih lain yang biasanya ditelurkan dengan metode induksi (istiqra’), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengamati dan mencari kesamaan dari semua permasalahan-permasalahan yang bertebaran di kitab fikih, lalu menarik benang merah persamaannya (asybah wan-nazhair), baru setelah itu dirumuskan menjadi kaidah fikih. Kaidah al-kharaj bidh-dhaman memiliki keunikan tersendiri karena pembentukan kaidah ini langsung dari hadis seperti yang telah penulis kemukakan di atas. Penerapan dari kaidah ini sangat banyak sekali dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya, kami uraikan sebagai berikut:
Pertama: Seorang budak yang digadaikan kemudian dimerdekakan oleh rahin (orang yang menggadaikan), maka status kemerdekaannya dianggap sah. Selanjutnya, si budak juga tidak perlu bekerja pada murtahin (orang yang menerima penggadaian), bila rahin termasuk orang yang kaya. Hal ini karena murtahin bisa menarik piutangnya dari rahin bila memang sudah jatuh tempo atau meminta jaminan lain bila masih belum jatuh tempo. Contoh kasus ini berbeda ketika pihak rahin termasuk orang miskin, maka si budak harus bekerja untuk murtahin dengan kadar biaya paling rendah dari penjaminannya atau hutangnya. Hal demikian dikarenakan rahin tidak bisa memenuhi tuntutan dari pihak murtahin ketika diminta membayar hutangnya atau jaminan lain, sehingga yang diambil adalah pemanfaatan dari budak tersebut.
Kedua: Bila pihak pembeli mengembalikan barang pembeliannya baik berupa hewan, rumah, atau mobil, dikarenakan ada aib yang tidak ia sadari setelah ia terima padahal ia sempat memanfaatkan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau dengan cara disewakan, maka ia tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi (upah) pada pihak penjual. Sebab, barang tersebut pada saat itu berada pada garansi kepemilikannya. Andai barang tersebut mengalami kerusakan pada saat itu, maka ia menjadi penanggung kerugiannya. Kasus ini berbeda bila pihak pembeli sebelum itu sudah mengetahui akan adanya aib pada barang pembeliannya, maka ia tidak boleh khiyar dan mengembalikan barangnya.[4]
Ketiga: Sekelompok orang bekerja sama untuk mendirikan perusahan otomotif dan masing-masing dari mereka saling menyalurkan pendanaannya sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan. Pada awal berdiri, ternyata perusahaannya menghasilkan omzet yang besar dan penghasilannya disalurkan pada masing-masing orang dari kelompok tersebut sesuai sahamnya. Di tahun-tahun selanjutnya ternyata terjadi kerugian, maka dalam hal ini mereka juga menerima bagian kerugiannya sesuai kadar nominal saham yang mereka salurkan.[5]
Epilog Secara umum, kaidah ini mencoba menghargai adanya penjaminan yang sebanding dengan pemanfaatan. Bila penjaminan digambarkan sebagai amal, maka pemanfaatan disamakan sebagai upah. Sehingga seseorang yang siap menanggung resiko atas segala kerugian atas sesuatu, maka sebaliknya ketika hal tersebut membuahkan untung ia juga berhak atas keuntungan, sebagaimana uraian hadis Rasulullah di atas. Wa’allahu A’lam bish-Shawab.
Oleh: Bahrussoleh/ Redaksi Istinbat
[1] HR. Ibnu Majah, III/753.
[2] Taudihu al-Ahkam fi Bulughi al-Maram, Hal 340.
[3] Abdul Ghaffar, Muhammad Hasan, Al-Qawaid al-Fiqiyah bainal-Ishalah wa at-Taujih, hal: 207.
[4] Ali Burnu, Muhammad Sidqi, al-Wajiz fi Idhohi Qawaid al-Fiqhi al-Kulliyah
[5] Abdu Al- Qhaffar, Muhammad Hasan, al-Qawaid al-Fiqiyah baina al-Isholah wa at-Taujih, Juz XVIII. Hal 10