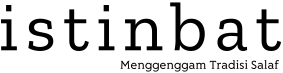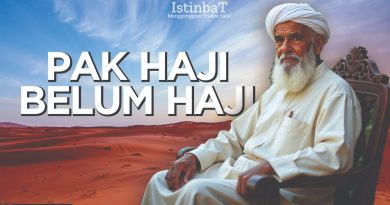Keterlibatan Orang Tua dalam Proses Belajar Anak
Anak merupakan amanah dari Allah ﷻ kepada orang tua. Hati mereka yang suci dan bersih bagai kertas putih, siap menerima pengajaran dan bimbingan. Jika dibimbing dengan kebaikan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Orang tua dan pendidik akan menuai pahala atas kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika dibiarkan tanpa bimbingan dan dibiasakan berbuat kejahatan, maka mereka akan mengalami kecelakaan dan orang tua akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.[1]
Kewajiban utama orang tua adalah mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai agama, mencakup aspek-aspek wajib dan sunah. Sayangnya, banyak orang tua yang mengandalkan lembaga pendidikan agama seperti madrasah atau pondok pesantren secara penuh.
Keterbatasan waktu dan kurikulum di lembaga mengakibatkan beberapa materi penting tidak tersampaikan secara utuh. Waktu libur panjang juga sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh orang tua untuk memperkuat pemahaman agama.
Lantas, apakah menyekolahkan atau memondokkan anak sudah cukup untuk membebaskan kewajiban orang tua dalam mendidik anak? Pertanyaan ini penting, mengingat keterbatasan yang ada di setiap lembaga pendidikan formal.
BACA JUGA: MENCIUM TANGAN ANTARA PERINTAH DAN LARANGAN
Dalil tentang pendidikan
Mendidik anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua. Sebagaimana firman Allah:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6)
Nabi Muhammad bersabda:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka, dan perempuan adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka.”
Menurut Imam an-Nawawi, kewajiban mendidik ilmu agama bagi orang tua terhadap anaknya dimulai sebelum mencapai usia baligh. Lebih tepatnya, setelah anak berusia tujuh tahun dan telah mencapai usia tamyiz (dapat makan, minum, dan beristinja’ sendiri).[2] Jika anak telah mencapai usia tamyiz sebelum berusia tujuh tahun, maka orang tua tidak memiliki kewajiban untuk mendidiknya, karena secara umum anak belum mampu menerima pelajaran dan melaksanakan perintah. Namun, disunahkan agar anak terbiasa melakukan kebaikan sejak dini.[3]
Imam ar-Rafii berkata bahwa para imam berpendapat, “Orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya tentang thaharah, shalat, dan syariat Islam setelah berusia tujuh tahun. Jika anak tidak melaksanakannya setelah berusia sepuluh tahun, orang tua berhak memberikan hukuman.”[4]
Anak wajib diperintah melakukan ketaatan seperti, shalat, thaharah, puasa, dan lainnya, serta dilarang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang berhubungan dengan Allah atau sesama manusia. Selain itu anak wajib dididik dengan budi perkerti yang baik serta dicegah melakukan akhlak yang tercela dan sesuatu yang menyalahi kebiasaan sekalipun bukan maksiat karena hal itu bagian dari kemaslahatan seorang anak.[5]
Tidak hanya itu, sebelum diajari shalat orang tua wajib mengajari anaknya pengetahuan dasar tentang agama yang harus diketahui oleh semua orang, baik yang umum ataupun yang khusus, yang dapat mengakibatkan kekafiran bagi orang yang mengingkarinya, seperti pengetahuan bahwa Nabi Muhammad diutus di Makkah dan dimakamkan di Madinah dan yang lainnya.[6]
Wilayah dalam mendidik
Kewajiban mengajari anak hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebagaimana yang dipaparkan Syekh al-Baijuri dalam Hasyiatul Baijuri,
“Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang taharah, salat dan syariat Islam lainnya sebagai kewajiban fardhu kifayah.Biaya pendidikan anak menggunakan harta anak itu sendiri, jika tidak ada, menggunakan harta orang tuanya, kemudian baitul mal, dan terakhir menggunakan harta orang kaya dari kaum muslimin.”[7]
Dan yang menjadi sasaran fardhu kifayah adalah orang tua, ayah, ibu, dan semua orang yang diberi amanah untuk menjaga dan merawatnya.[8] Kewajiban perintah ini terus dilakukan selama ada dugaan kuat (zhan) bahwa perintah belum dikerjakan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj:
“Perintah tanpa ancaman tidak cukup. Menurut Syekh al-Bashri, perintah harus diulang jika tidak efektif. Apakah perintah satu kali cukup atau perlu diulang untuk setiap shalat? Atau apakah perlu diulang jika ragu-ragu tentang pelaksanaan perintah sebelumnya? Hal ini membutuhkan pertimbangan lebih mendalam dan yang ketiga paling mendekati.”
Menurut Syekh Hasan bin Muhammad al ‘Aththar dalam kitab Hasyiyatul ‘Aththar ‘ala Jam’il-Jawami’, kewajiban fardhu kifayah ditentukan berdasarkan dugaan kuat (zhan). Jika suatu kelompok yakin bahwa kelompok lain akan melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi mereka. Sebaliknya, jika suatu kelompok yakin tidak ada kelompok lain yang melaksanakannya, maka seluruh kelompok wajib melaksanakannya.[9]
Dari sini dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua bisa gugur jika mereka memondokkan atau menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang menyediakan pengajaran lengkap tentang ilmu-ilmu wajib, seperti pondok pesantren salaf, dengan adanya dugaan kuat bahwa anak tersebut telah menerima pendidikan yang memadai.
Ala kulli hal, kewajiban orang tua dalam mendidik anak tidak berhenti hanya karena anak disekolahkan ke lembaga pendidikan. Orang tua harus terus memantau dan mendukung proses pendidikan anak untuk memastikan mereka menerima pendidikan yang memadai. Wallahu a’lam bis shawab.
BACA JUGA: KITA SERING LUPA KEBAIKAN ORANG TUA
Faqihuddin/Sekred IstinbaT
[1] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, III/62.
[2] Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, al-Hawi al-Kabir, II/313.
[3] Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, Nihayatul-Muhtaj ila Syarhil-Minhaj, I/301.
[4] Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, Majmu’ Syarhul-Muhadzdzab Lisy-Syirazi, III/11.
[5] Zakariya al-Anshari, Asnal-Mathalib, IV/162.
[6] Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I’anatuth-Thalibin, I/35.
[7] Ibrahim al-Bajuri, Hasyiatul-Baijuri, I/252.
[8] Sulaiman bin Umar, Hasyiyatul-Jamal, II/50.
[9] Hasan bin Muhammad al-‘Aththar, Hasyiyatul ‘Aththar ‘ala Jam’il-Jawami’. II/62.