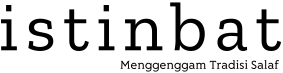Thufi, Sang Promotor Ushul Fikih Liberal
Dalam edisi kali ini penulis tertarik membahas pemikiran seorang tokoh abad ketujuh Hijriah, Najmuddin ath-Thufi,1 seorang tokoh kontroversial pengusung Ushul Fikih Liberal. Pandangannya seputar kemaslahatan telah mencuri perhatian para tokoh kontemporer seperti Dr. Musthafa Zayd dan tokoh-tokoh Mesir lain di eranya.
Dalam pandangan Thufi, dari 19 dalil hukum Islam, yang paling kuat adalah nash dan ijmak. Keduanya adakalanya selaras dengan maslahat dan adakalanya bertentangan. Jika dalam kenyataannya selaras, maka tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, jika dalam kenyataannya terjadi kontradiksi, maka maslahat harus lebih diutamakan dari nash dan ijmak dengan pendekatan takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan) terhadap keduanya. Dari sini Thufi menetapkan bahwa menjaga kemaslahatan adalah dalil yang lebih kuat dari pada nash dan ijmak. Secara tegas ia mengatakan, “(Dalil) menjaga kemaslahatan lebih kuat daripada nash dan ijmak karena dalil yang lebih kuat dari dalil lain (yang juga lebih kuat) adalah dalil terkuat.”
Fokus pembahasan yang akan penulis sajikan adalah pokok pemikiran Thufi di atas dan dalil yang dijadikan landasan olehnya. Di antara metodologi yang menjadi landasan Thufi dalam mendahulukan maslahat atas nash dan ijmak adalah:
Pertama, dalil ijmak masih menjadi perdebatan panjang di antara ulama, sedangkan menjaga kemaslahatan adalah dalil yang mencapai tingkatan ‘mufakat’. Berpedoman pada hal yang disepakati dan mengesampingkan sesuatu yang masih diperdebatkan itu lebih utama.
Kedua, nash yang ada berbeda-beda dan kontradiktif. Menurutnya, hal inilah penyebab munculnya perbedaan ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan memelihara kemaslahatan pada hakikatnya merupakan prinsip hukum yang disepakati dan tidak diperselisihkan, dan terbukti ada pertentangan antara nash-nash sunah (hadis) dengan maslahat dalam beberapa masalah. Oleh karena demikian, mendahulukan maslahat dalam penetapan hukum menjadi skala prioritas dan keniscayaan.
Statement Thufi tersebut tentunya perlu ditelaah ulang. Bangunan pemikirannya dianggap rapuh dan berseberangan dengan pandangan mainstream. Konstruksi pemikirannya cenderung mendasarkan pada superioritas akal manusia. Baginya akal berfungsi memetik nilai kemaslahatan dengan mengesampingkan teks al-Quran dan Hadis. Sehingga tak heran jika banyak ulama yang menentang teori yang ia sampaikan.
Berikut penulis paparkan beberapa poin kesalahan pandangan Thufi. Pertama, kontruksi yang dijadikan dasar dari praduga Thufi adalah perkara yang muhal serta tidak mungkin terjadi, yaitu pernyataan bahwa maslahat menyalahi terhadap nash dan ijmak. Kitab Allah telah memberi petunjuk bahwa yang terkandung di dalamnya hanyalah rahmat pada hamba dan menjaga kemaslahatan mereka. Oleh karenanya nash-nash al-Quran datang selaras dengan maslahat ini. Sehingga dapat dikatakan muhal jika ditemukan ayat dalam al-Quran menyalahi terhadap maslahat yang hakikat. Barangkali kontradiksi yang tampak pertama kali karena pengaruh syahwat dan lemahnya akal kita dalam menggali makna maslahat yang sebenarnya.3
Kemudian, andaikala kita katakan bahwa ada nash al-Quran yang menyalahi terhadap maslahat, maka hal ini justru menjadi bumerang yang akan merusak pondasi yang dijadikan landasan pemikiran Thufi, yaitu syariat dibumikan hanya demi menjaga kemaslahatan seorang hamba. Hal ini menjadi bukti bahwa cakupan nash-nash lebih umum dari keharusan menjaga maslahat, atau dapat dikatakan ada tugas lain dari nash selain menjaga maslahat. Oleh karenanya, pertimbangan maslahat tidak mampu untuk mengetahui dan menelurkan hukum-hukum syariat.
Kedua, anggapan bahwa maslahat lebih kuat daripada nash dan ijmak adalah kata lain dari menjadikan maslahat sebagai dalil independen (dalil mustaqil). Padahal ulama mengatakan bahwa menjaga kemaslahatan bukanlah dalil independen.
Ketiga, dasar metodologi yang digunakan Thufi dalam mendahulukan maslahat dari nash dan ijmak problematis. Jika yang ia kehendaki adalah realitas menunujukkan bahwa nash syariat dibangun atas dasar maslahat, maka pernyataannya benar. Namun, apa hubungan hal ini dengan statement-nya? Apakah kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa syariat dibangun atas dasar maslahat juga menetapkan kesepakatan mereka atas pendahuluan maslahat dari nash dan ijmak? Hal ini jelas pemikiran yang pincang.4
Namun jika yang ia kehendaki adalah para ulama yang mengingkari ijmak berpendapat sebagaimana yang ia katakan, maka hal ini jelas sebuah kebohongan besar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak satupun ulama sebelum masanya berpendapat sebagaimana dirinya, baik ulama yang mengatakan kehujahan ijmak atau yang menafikanya.
Keempat, terkait ungkapannya bahwa nash itu berbeda-beda dan kontradiktif. Ini adalah pernyataan yang keliru besar. Bagaimana tidak? Nash al-Quran itu datang dari sisi Allah. Tidak mungkin ada perbedaan dan kontradiktif antara satu ayat denga yang lain. Dengan praduga ini Thufi ber-istidlal bahwa khilaf yang terjadi antara para imam dan fukaha disebabkan oleh perbedaan nash. Padahal khilaf yang terjadi di antara mereka didalam furu’ karena perbedaan sudut pandang dalam memahami nash-nash demi mencapai pada hakikat madlul-nya. Bukan khilaf antara nash-nash itu sendiri.5
Terakhir, penulis tampilkan komentar yang disampaikan oleh Khallaf terkait pandangan Thufi. Khallaf dalam kritiknya mengatakan bahwa pemberian otoritas maslahat yang berdasarkan akal sebagai dalil hukum terkuat dapat membasmi nash, dan menjadikan hukum nash atau ijmak bisa dianulir oleh sebuah pendapat. Karena bagaimanapun, maslahat hanyalah sebuah pendapat yang disimpulkan oleh akal. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa maslahat bersifat relatif. Maka sangat mugkin terjadinya sesuatu (hukum) yang mulanya dikira maslahat, justru menghasilkan sebuah mafsadat. Hal ini berbahaya serta mengancam eksistensi syariat hukum Islam itu sendiri.
Oleh: Abdul Basith
Referensi dan Catatan Kaki:
- Najmuddin ath-Thufi (675-716 H) adalah seorang pakar dibidang yurisprudensi Islam, Ushûl Fiqh (legal theory), dan Hadîs. Nama lengkapnya Abûr-Râbi’ SulaImân bin ‘Abdul Qawi bin ‘Abdul Karîm bin Sa‘îd ath-Thufi. Lebih populer dengan Najmuddin ath-Thufi. Nama ath-Thufi diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Baghdad, Irak. Dalam bidang Fikih, pada mulanya dia pengikut mazhab Hanbali, setelah itu membelot dari ushul dan furu’-nya Hanbali. Di bidang akidah, awalnya pengikut Ahlusunah, dan selanjutnya berpindah ke Syiah. (Keterangan biografi selengkapnya lihat dalam Dhawabit al-Mashlahah fisy-Syari’ah al-Islamiyyah, hal. 178).
- Ath-Thufi, Abûr Râbi’ Sulaimân bin ‘Abdul Qawi bin ‘Abdul Karîm bin Sa‘îd, Risalah fi Ri’ayatil Maslahah, Pentahkik, Dr. Ahmad Abdur Rahim, Darul Mishriyyah al-Libananiyyah, hal. 23-24.
- Al-Buthi, Dr. Muhammad Sa’îd Ramadhan, Dhawabitul Mashlahah fisy-Syari’ah al-Islamiyyah, Muassasah al-Risalah: Dar al-Muttahidah, cet. VI, 2000, hal. 127-133.
- Ibid
- Ibid