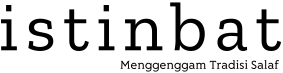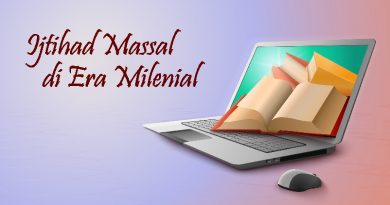MEMBIDIK BAHASA RIDHA DALAM KAIDAH
“RELA PADA SUATU PERKARA BERARTI RELA PADA APA YANG TERLAHIR DARINYA”
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengkaji salah satu cabang penerapan dari kaidah, yaitu kaidah Ar-ridha bisy-syai’ ridha bima yatawalladu minhu, artinya “Rela pada suatu perkara berarti rela pula pada apa yang terlahir darinya”
Ungkapan rela pada suatu perkara juga berarti mengizini padanya. Hukum yang keluar dari ungkapan rela ini tidak semerta-merta menunjukan hukum boleh (ibahah), tetapi bisa menjadi hukum boleh, dimaafkan, halal, tidak batal, dan tidak ada hukuman. Pada intinya semua itu menunjukan tidak ada masalah jika adanya sesuatu itu muncul dari perkara yang awalnya sudah diridai.
Manusia harus memiliki komitmen kuat terhadap apa yang mereka putuskan. Konsekuensi yang timbul akibat keputusan dan perbuatannya harus diterima, baik sifatnya positif atau negatif. Hikmah inilah yang menjadi esensi dari rumusan kaidah ini.
Secara implisit, kaidah ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menentukan sikap, tidak ceroboh dalam melangkah, dan berfikir matang sebelum berbuat. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Sebab, ketika seseorang telah menyatakan rela atau setuju, maka konsekuensinya ia harus rela menanggung akibat yang ditimbulkan oleh pernyataannya itu.
Dalam semua pembahasan kaidah ini yang meliputi persetujuan, kerelaan, pengesahan, perizinan, dan lain sebagainya masuk pada kaidah di bawah ini. Kerelaan tersebut bisa berasal dari siapa saja dan berupa apa saja. Bisa berbentuk pernyataan resmi atau bisa pula berupa hal –hal yang diberlakukan dan telah legistimasi oleh syariat sebagaimana kaidah
المتولد من مأذون فيه لا أثر له
“Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapat ijin tidak memiliki dampak apapun” yang hampir menyamai kaidah yang akan kita bahas saat ini.
Penerapan kaidah
Penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagaimana berikut:
Pertama, sebut saja Dea dan Dani. Mereka telah lama menikah hingga mereka tau kekurangan masing-masing. Sepanjang masa berjalan, mereka pun telah rela akan kekurangan masing-masing. Waktu terus berlalu, hingga cacat yang ada pada Dea pun semakin parah. Dalam kasus ini Dani tidak bisa menceraian Dea karena bertambahnya cacat yang dialami Dea itu muncul dari cacat yang pertama, oleh karena itu, rela dengan cacat sebelumnya berarti rela dengan tambahan yang ada. Begitu juga sebaliknya, Dea tidak dapat mengajukan talak lantaran cacat yang diderita Dani semakin parah. Dengan catatan, cacat yang dimaksud memang sudah direlakan saat pertama kali mereka mengikat tali pernikahan[1].
Kedua, penerapan kaidah ini juga mencakup kepada penbahasan istinja’. Pasalnya jika ada orang buang air besar (BAB), kemudian dia tidak menemukan air untuk dibuat membasuh tempat keluarnya kotoran, maka langkah selanjutnya yang harus ia lakukan adalah menghilangkan kotorannya dengan menggunakan batu, asalkan syarat-syarat bagi orang yang istinja’ menggunakan batu telah terpenuhi. Mari kita perinci, hukum setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan yaitu Qubul dan Dubur adalah haram, oleh karena itu jika ada orang buang air besar kemudia dia menggunakan batu untuk menghilangkan kotorannya, maka permasalahan ini tergolong hal yang ditolerir (ma’fu), dengan catatan, bagian tempat keluarnyna kotoran sudah kering dan tidak meningggalkan bekas secara kasat mata. Jika kemudian ia berkeringat dan membasahi area tersebut, maka menurut pendapat yang paling valid (ashah) ia tetap mendapat toleransi (ma’fu). Artinya bagian tempat keluarnya kotoran yang pastinya masih ada sisa kotorannya itu tidak dihukumi najis, melainkan di–ma’fu (dimaafkan), tetapi bagi dia tetap wajib membasuhnya hingga bersih total karena di-ma’fu bukan berarti suci, tetapi najis[2].
Ketiga, jika ada orang memakai wangi-wangian sebelum melaksanankan ihram, tetapi wanginya bertahan sampai pada waktu ihram[3] maka tidak dikenai fidyah.
Pengecualian
Kaidah ini tidak dapat diberlakukan dalam aktivitas yang syaratkan untuk menjaga keselamatan dari akibat yang mungkin ditimbulkan. Artinya, jika terjadi efek yang merupakan dampak dari perbuatan yang seharusnya dapat dihindari, maka kerelaan, izin, atau legalitas yang diberikan tidak begitu saja menjadikan ditolerannya akibat yang ditimbulkan untuk memudahkan pemahaman, kita cermati contoh berikut:
Seorang pembina yang menghukum muridnya karena melakukan pelanggaran dan telah mendapat izin sang wali jika hukuman itu sangat berat hingga menimbulkan dampak yang tidak diduga sebelumnya, yakni meninggal, maka takzir tersebut harus dipertanggungjawabkan (dhaman). Perlu dicatat, takzir adalah hal yang direstui oleh syariat. Tetapi, dalam kasus ini, sang guru tetap wajib bertanggung jawab karena seberapapun izin yang diperoleh seorang guru dari wali murid maupun dari syariat, tetaplah terbatas pada ketentuan menjaga keselamatan dampak yang mungkin timbul.
Contoh di atas sedikit memberi kita pemahaman, pada dasarnya selain memberi hukuman, seorang guru jika masih bisa menjatuhkan hukuman lain yang lebih manusiawi, misalnya menasehati, memberi contoh teladan, mengingatkan, menyindir, memarahi, dan lain sebagainya, maka sang guru seharusnya memilih solusi ini terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, maka langkah selanjutnya dimulai dengan kekerasan yang tidak terlalu parah, kemudian berlaku seterusnya.
oleh : Moch. Ruslan Abizar
Referensi :
[1] Al-ghurar al-bahiyah fi Syarhil Qawaid al-fiqhiyah, hal:122
[2] Anfusuz Zahair fi Syarhil Asybah wan Nadzair, hal:154
[3] Berihram adalah niat memasuki aktivitas ibadah haji atau umroh pada waktu serta cara tertentu. Prof Quraish Shihab dalam bukunya “Haji dan Umrah Bersama M.Quraish Shihab”